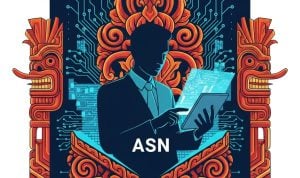Sistem pengetahuan tersebut, dilacak dan dikumpulkan dari berbagai struktur ide sampai praktik hidup masyarakat sehingga dapat dijadikan—paling tidak— sebagai kerangka acuan pembelajaran dan pemahaman lebih lanjut terkait multikulturalisme. Sebab sejak semula, lanskap sosiokultural di Indonesia adalah kemajemukan dan pluralitas. Yang menjadi persoalan lanjutan kemungkinan terletak pada bagaimana sikap atau perspektif pemangku kepentingan dalam memaknainya. Alangkah indah bila yang ‘diaminkan’ adalah keberterimaan terhadap kemajemukan yang niscaya tersebut. Lantas celakalah bila yang dijadikan pedoman berpraktik sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah ‘melabeli’ sekaligus ‘menyingkirkan’ yang berbeda itu. Seperti kasus pelemahan fungsi ritual Bissu di HJB Bone beberapa waktu lalu.
Pelik persoalan ‘peminggiran’ komunitas budaya seperti Bissu pada perayaan HJB ke-692 barangkali bukan yang pertama terjadi di negeri ini. Banyak dan akan bertambah kasus serupa dalam wujud yang berbeda jika pemahaman tentang kemajemukan dan pluralitas sosiokultural negeri ini dikerdilkan menjadi pemahaman ‘puritanisme’. Entahkah bentuknya puritanisme budaya terlebih puritanisme agama. Keduanya sama-sama menyimpan ‘senjata pemusnah massal’. Kondisi terparah terjadi ketika ‘kegenitan puritanisme’ ini masuk sampai ke dalam sendi-sendi pikiran individu dalam institusi pemerintahan. Sudah barang tentu akan terjadi sebuah bencana maha dahsyat; Kiamat Kebudayaan. (*)