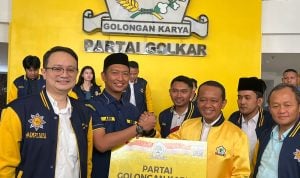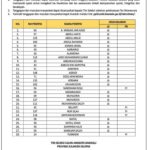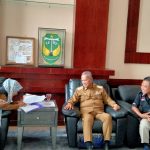HARIAN.FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Kelompok minoritas masih kerap mendapatkan diskriminasi. Baik dari sisi regulasi, maupun dalam bentuk perundungan atau persekusi.
Manusia lanjut usia (lansia), disabilitas, anak danperempuan, Bissu, Tolotang, dan kelompok kurang berdaya lainnya, bahkan masih kerap mendapatkan perlakuan tak adil dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk LGBT.
Padahal, sebagai sesama warga negara, mereka sama-sama berhak atas kehidupan yang aman dan mendapatkan perlindungan dari negara. Di sisi lain, apa yang terjadi pada mereka bukanlah keinginan, melainkan pemberian (given).
Tak ada seorang pun pernah meminta untuk menjadi difabel, anak, perempuan, lansia, penganut kepercayaan tertentu, kelompok spiritual budaya, bahkan LGBT. Mereka mendapati diri masing-masing seperti itu sebagai sesuatu yang ada dengan sendiri.
Dengan situasi tanpa pilihan itu, mereka dipaksa menjadi “normal” selayaknya manusia mayoritas pada umumnya. Publik masih menganggap diri mereka terbaik, yang berbeda tidak baik.
Stereotipe semacam inia kan terus menerus melanggengkan diskriminasi terhadap mereka, baik dari sisi perlindungan negara, maupun hak asasi manusia (HAM).
Kelompok minoritas masih selalu menjadi subjek yang dilekatkan stigma negatif. Menjadi sasaran perundungan (bullying), cemoohan, bahkan mengalami kekerasan, baik dari kelompok sipil maupun aparat negara. Terutama LGBT yang masih kesulitan mendapatkan hak-hak konstitusional terkait dengan ekspresi mereka.
“Pada 2015 ke bawah, diskriminasi itu banyak dilakukan kelompok masyarakat atau ormas,” beber Gupta, aktivis penggerak HAM di Makassar, Minggu (17/11/2024).
Selanjutnya, 2016 hingga kini, diskriminasi atas kebebasan berekspresi kelompok minoritas, khususnya LGBT, bahkan bergeser. Pelaku melibatkan aparat negara dalam bentuk mempersulit kegiatan. Proses penerbitan perizinan kegiatan dipersulit, bahkan ikut serta membubarkan kegiatan atas hasutan ormas yang antiminoritas.
Pandangan negatif yang dikonstruksi kekuasaan mayoritas memperparah kondisi mereka. Mereka kerap dicap sebagai pembawa bencana dan kesialan, penyebab penyakit menular, pelaku sodomi, perilaku menyimpang, korban trauma masa lalu, bahkan terparah dianggap kafir dan penghuni neraka jahanam.
Padahal, dalam semua aspek sosio-kultural, perilaku semacam itu ada. Parahnya, praktik negatif yang disematkan kepada minoritas, justru kerap terjadi di lingkungan “religius” sekalipun. Di sekolah keagamaan kerap ditemukan kasus sodomi bahkan pemerkosaan oleh pembina atau pengelola.
Akar Problem
Diskriminasi terhadap minoritas muncul karena adanya peran “kekuasaan” dalam arti luas pada kehidupan bermasyarakat. Akar masalah ketidakadilan dan represi terhadap mereka muncul dari sikap patriarki kelompok mayoritas yang minim pemahaman atas hak-hak warga negara dan HAM.
Kondisi itu juga terlembagakan dalam bentuk manifestasi tafsir atas teks keagamaan. Sementara, ada situasi yang memungkinkan interpretasi berbeda atas status quo yang dominasinya merentang begitu panjang.
Setidaknya, ada tiga faktor yang membuat perilaku an sich terhadap kelompok minoritas itu terjadi. Pertama, faktor heteronormativitas. Suatu kepercayaan yang menganggap bahwa heteroseksualitas adalah norma dan satu-satunya bentuk seksualitas yang alami dan dapat diterima.
Heteronormativitas juga mengacu pada gagasan bahwa semuaorang harus menyesuaikan diri dengan peran dan hubungan gender tradisional. Pandangan ini dapat memengaruhi semua anggota masyarakat sejak lahir.
Dalam praktik heteronormativitas pada kehidupan sehari-hari, ada sebentuk “keyakinan” sepihak yang menganggap bahwa hubungan normal hanya ada antara pria dan wanita. Ada pula anggapan bahwa laki-laki yang hobi masak dan nonton Masterchef di TV, misalnya, sebagai seorang yang “bermental” cewek.
Pandangan heteronormativitas ini dapat merugikan kaum minoritas seksual dan melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan. “Pandangan ini bertentangan dengan homoseksual,” papar Gupta.
Kedua, faktor gender superior. Di sini, ada anggapan atau pandangan bahwa salah satu jenis kelamin (biasanya laki-laki) lebih superior atau lebih unggul dibandingkan jenis kelamin lainnya (biasanya perempuan). Konsep ini sering kali tercermin dalam sistem sosial, budaya, dan struktur yang mendukung ketidaksetaraan gender. Salah satu gender diberikan keistimewaan, hak, atau posisi lebih tinggi daripada yang lain.
Dalam masyarakat yang menganut ideologi gender superior, sering terjadi diskriminasi atau marginalisasi terhadap gender yang dianggap lebih rendah. Misalnya, dalam konteks patriarki, laki-laki dianggap lebih berkuasa atau lebih kompeten, perempuan dan gender lain sering kali diposisikan sebagai pihak yang lebih lemah atau tidak setara.
Pandangan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, yang menekankan semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau gender, memiliki hak yang setara dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan.
Dalam konteks modern, ideologi gender superior sering dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender yang harus diatasi untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
Ketiga, faktor gender biner. Istilah ini berangkat dari teori “binary opposition” atau oposisi biner yang dicetuskan antropolog Prancis, Claude Levi-Strauss. Kunci utama dari pandangan ini adalah kesimpulan radikalnya pada isi dunia yang dianggap berhadap-hadapan atau berpasang-pasangan.
Teori ini melanggengkan penapian terhadap di luar dari gender yang “diakui” mayoritas alias menempatkan segala sesuatu sebagai dua hal yang berlawanan. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Tua lawannya muda, utara lawannya selatan, laut lawannya daratan, dll.
Padahal, di antara semuanya, ada “entitas lain” di luar dari kutub berlawanan itu. Di antara tua dan muda, ada fase dewasa. Di antara utara dan selatan ada “middle”, di antara laut dan daratan ada pantai, dan di antara laki-laki dan perempuan ada gender lain, semisal transpuan dan transman atau lainnya.
Bahkan dalam konteks kebudayaan Sulsel, sejarah mencatat terdapat lima gender. Masing-masing horoane atau burane (laki-laki), makkunrai atau baine (perempuan), calalai (transpuan), calalaki (transman), dan Bissu (kelompok spiritual kebudayaan lampau Pulau Sulawesi).
“Gender biner cuma mengakui laki-laki dan perempuan,” papar Gupta.
Komoditas Politik
Upaya mempertahankan status quo stereotipe itu pun terus bermetamorfosis dalam bentuk banyak wajah. Mereka masuk melalui pendidikan, kebudayaan, hukum, interpretasi agama, dan termasuk pembentukan opini media.
Di dunia politik, kelompok minoritas yang di dalamnya terdapat LGBT, bahkan kerap menjadi komoditas politik. Mereka didekati kala pemilihan, namun dijauhi kala terpilih.
Bahkan dalam kasus ekstrem, mereka ditindas berkali-kali. Dijadikan kendaraan atas nama agama oleh kandidat, sebagai kelompok yang akan “dibina”, sehingga memicu reaksi dan emosi kelompok status quo.
Pada Pilgub Sulsel 2024, Gupta mengakui belum ada sosok yang benar-benar ideal sebagai “pengayom” kelompok berbeda. Minoritas masih menganggap dunia politik sebagai dunia yang dipenuhi “prank” alias janji-janji palsu.
“Belum ada niat membuat kontrak politik,” kata Gupta. Ide kontrak politik ini sempat muncul untuk memasukkan gagasan perjuangan persamaan hak dan kesetaraan kelompok minoritas, terutama LGBT, namun dianggap langkah itu berpotensi memicu penolakan superioritas terhadap mereka.
Pada akhirnya, kelompok minoritas tak memaksa kelompok mayoritas untuk menjadi mereka. Pun tak meminta untuk diperlakukan spesial. Yang paling penting, hak-hak kewarganegaraan dan HAM mereka terpenuhi, sama seperti warga negara pada umumnya.
“Orang tidak harus sama dengan kami. Bahkan boleh menolak kami sebagai sikap personal, tapi itu cukup di kepala, tidak membuat hal-hal yang merugikan kami, dan melihat kami sebagai manusia,” pinta Gupta.
Jaminan Konstitusi
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Didit Haryadi mendorong jurnalis untuk berlaku adil bagi semua warga negara, yang didalamnya juga terdapat kelompok minoritas. Mereka juga memiliki hak ekspresif, sama seperti warga negara pada umumnya.
Bahkan, kebebasan berekspresi itu mendapat jaminan dari induk regulasi di Indonesia, yakni UUD 1945. Tak hanya bagi kelompok mayoritas, namun juga bagi minoritas yang dalam sejumlah kasus dan pengalaman sejarah, seringkali menjadi korban diskriminasi.
“Sebenarnya semua orang punya hak yang sama, karena itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Jadi tidak boleh ada diskriminasi,” beber jurnalis Tempo itu.
Sejumlah kegiatan kelompok minoritas dan LGBT mendapat penentangan, bahkan kerap dibubarkan. Selaku manusia yang hidup dalam negara demokrasi dan berpayung konstitusi, tidak semestinya hal tersebut terjadi pada mereka.
“Kebebasan berekspresi itu adalah hak mendasar dalam kehidupan yang karena itu harus dilindungi oleh negara,” papar Didit.
Pantauan Medsos
Aktivis Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, Musdalifah Jamal juga menyoroti peran Pemprov Sulsel yang cenderung mengabaikan hak-hak kelompok minoritas. Kasus penerbitan surat edaran tentang LGBT membuktikan adanya bias dalam proses pengambilan keputusan.
Secara umum, di antara dua paslon pada Pilgub Sulsel 2024, tak ada satu pun yang menyentil tentang LGBT. Bisa jadi, ini merupakan bentuk kehati-hatian mereka lantaran bisa berpengaruh terhadap elektabilitas.
Baik di media sosial pribadi masing-masing kandidat, maupun pada dua kali debat publik Cagub-Cawagub Sulsel, tidak ada yang membahas soal LGBT. Termasuk dari paslon nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) dan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati). (*)