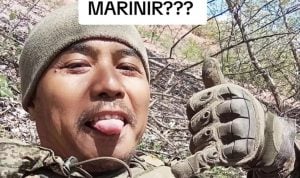MAKASSAR, FAJAR–Politik tak bermakna apa-apa bagi mereka. Bissu terkucilkan di ruang riuh itu.
Tatapannya nanar. Bulir bening menggelayut di selaput matanya. Kalimatnya terbata-bata setiap kali menceritakan ruang derita dalam perjalanan hidupnya sebagai “penjaga” kebudayaan lampau Sulsel.
Dialah Puang Matoa Bissu Neni Ramli. Selama musim Pileg-Pilpres 2024, nyaris tak ada kandidat yang mendatanginya. Tak ada visi-misi calon tertentu yang ia ketahui. Kelompok politik tak pernah datang ke tempatnya.
“Tidak ada caleg yang datang ke istana (ini),” ujar Bissu Neni dalam bahasa Bugis kental kala FAJAR mengunjunginya di Istana Arajang Segeri, Pangkep, Sabtu (17/2/2024).
Arajang adalah istana untuk pimpinan dan bissu aktif. Sejak dahulu mereka memiliki istana di Segeri. Sejak zaman kerajaan, hingga Indonesia merdeka, istana itu selalu ada. Gelar “Puang Matoa” merupakan level tertinggi dalam komunitas bissu.
Puang Matoa merupakan pimpinan atau bissu tertinggi di Arajang Segeri, Pangkep. Arajang sendiri berdiri di suatu hamparan lahan luas di Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Pangkep.
“Biasa (tokoh) ada yang datang, tapi kami tidak bisa ke mana-mana kalau tidak dipanggil (diundang),” lanjut Bissu Neni.
Neni menjadi bissu sejak usia 15 tahun. Dia mendapat pammaseang (ilham) dari La Marupa (istilah untuk mewakili Tuhan pada masa lampau). Saat itu, dia masih tinggal di Bonto-bonto, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep.
Dengan jabatan sebagai Puang Matoa, Bissu Neni menjadi penerus Puang Matoa Bissu Saeke, Puang Matoa Bissu Sanro Polleng, Puang Matoa Bissu Puang Baji, Puang Matoa Bissu Puang Mase, Puang Matoa Bissu Barliang, dan Puang Matoa Bissu Saidi.
Nama terakhir merupakan Puang Matoa yang posisinya kini diambilalih oleh Bissu Neni. Puang Matoa Saidi bin Rudding meninggal pada Selasa, 28 Juni 2011. Tak lama berselang setelah kematiannnya, Bissu Neni lalu didaulat menjadi Puang Matoa, yang artinya menjadi pemimpin spiritual di kalangan bissu Segeri.
Saat ini, di istana Arajang Segeri, Puang Matoa Neni tinggal bersama seorang adik perempuannya yang bukan bissu. Neni sendiri enam bersaudara. Di tengah merosotnya kepedulian pemerintah terhadap bissu, mereka tetap berupaya bertahan. Meski kerap kebutuhan mereka tak cukup.
“Jadi itulah beragam yang dilakukan. Misalnya menjadi perias pengantin kalau ada yang memanggil. Kalau tidak ada, ya, tinggal di rumah, kasihan. Memelihara ayam atau itik. Begitulah kehidupan bissu,” sambung Neni.
Memang, kadang ada bantuan dari pemerintah, tetapi tidak simultan. Bantuan keuangan itu hanya sesekali, misalnya ketika ada acara kebudayaan. Salah satunya ritual memindahkan barang-barang kerajaan.
Sejatinya, bissu bisa mandiri. Sebab, ada warisan lahan yang turun temurun mereka garap, hingga pada era kepemimpinan Puang Matoa Saidi. Sayang, karena ketiadaan administrasi otentik, lahan itu berpindah tangan.
“Seusai pelantikan setelah meninggalnya Bissu Saidi, saya disampaikan bahwa ada empang kecil yang bisa digarap,” kata Neni. Sayang, empang itu tak pernah diberikan kepadanya.
Setiap kali pejabat datang ke arajang, Bissu Neni selalu dijanjikan akan diberi tunjangan sekali sebulan. Hingga kini, itu juga tak terealisasi. Bissu Neni tak mengenal dan ingat lagi nama pejabat itu, tetapi soal janji mereka, dia masih ingat.
“Yang menjanjikan itu adalah (anggota) DPRD, bupati, dan camat kala itu,” urai Neni.
Dalam kehidupan keseharian kala tak ada ritual adat, tugas sehari-hari Puang Matoa Neni adalah membersihkan kerajaan dan benda-benda kerajaan. Sesekali ia menggelar ritual khusus bissu di dalam ruangan khusus. Dia tak bisa ke mana-mana lantaran arajang tidak bisa ditinggalkan alias tak bisa kosong.
Pemerintah juga disebutnya pernah menjanjikan akan memperbaiki istana arajang. Memang sudah pernah baik, tetapi sekarang rusak lagi. Bocor di mana-mana dan air hujan masuk. Plafon dan beberapa kayu lapuk karena rembesan hujan. “Sangat parah, dari dalam sampai ke luar,” kata Bissu Neni.
Sejak dahulu istana bissu ini sudah ada, bahkan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Sudah banyak Puang Matoa (pimpinan bissu) yang berpulang di istana ini.
“Sudah banyak sekali bissu yang meninggal, Nak. Yang hidup sisa Bissu Julaeha, Salemmang, dan Eka,” sambungnya.
Orang tua Bissu Neni bukan bissu. Mereka adalah petani yang menggarap sawah. Khusus pakaian kebesaran, mereka menggunakan baju dan sarung putih. Tidak bisa dicampur. Kala maggiri juga pakai baju putih.

Pergeseran Peran
Salah seorang bissu yang kerap diundang sebagai pembicara, Bissu Eka, merasakan adanya perbedaan kondisi masa lalu dan kini bagi eksistensi bissu. Fungsi dan peranan bissu masa lalu dan sekarang sudah banyak pergeseran.
“Hampir 360 derajat. Dahulu, bissu itu peran mereka sebagai penyambung lidah kerajaan di istana raja,” urai Bissu Eka kepada FAJAR di kediamannya di Segeri, Pangkep.
Dahulu, bissu bertugas sebagai penjaga permaisuri raja, sekaligus sebagai penjaga pusaka keramat kerajaan. Bissu juga ahli makanan atau dikenal dengan “jennang”. Karena fungsi di dalam istana itu, bissu tak perlu repot-repot mengurusi urusan duniawi, termasuk untuk kebutuhan sandang, papan, dan pangan.
Kerajaanlah yang akan menyediakan itu semua bagi mereka. Bissu hanya fokus pada tugas “penjaga nilai” dan menjaga hubungan “transenden” dengan ilahi.
“Bissu dulu tidak berkeliaran seperti saat ini, mencari nafkah sendiri seperti apa yang kita lihat,” sambung bissu yang baru saja pulang berhaji di Tanah Suci tahun lalu itu.
Jika membandingkan kondisi bissu masa lalu dan kini, Bissu Eka mengakui dirinya pun sudah menyimpang dari ajaran bissu dulu yang sebenarnya. Situasi yang memaksanya demikian. Dia harus melanjutkan hidup.
“Mestinya saya tinggal di arajang (istana kerajaan) sana, tetapi siapa yang biayai hidup saya, makan dan minum, kebutuhan saya,” lirih Bissu Eka.
Pada masa kerajaan, para bissu tidak berpikir panjang lebar. Dahulu, lantaran bissu berada di dalam istana, segala sesuatunya sudah terpenuhi dan sudah tercukupi oleh raja.
Apalagi, kala itu bissu merupakan penasihat spiritual bagi raja. Bissu menjadi “konektor” di antara langit tengah dan dunia. Bisu menjadi perantara dengan dewata (Tuhan).
Dalam kepercayaan Bugis kuno, dunia dibagi ke dalam tiga bagian. Ada botting langi (dunia atas), ale lino (dunia tengah), dan perettiwi’ (dunia bawah). Dunia bawah ini yang merupakan tempat bermukimnya dewa (i) atau Tuhan yang digambarkan berada di bawah laut.

Persentuhan Politik
Bissu termasuk kelompok kebudayaan dan minoritas yang tak begitu melirik dan dilirik dalam konteks politik. Belum pernah ada bissu yang masuk dalam dunia politik praktis. Baik di level legislatif, maupun eksekutif (pilkada, dll).
“Tidak ada bissu jadi caleg,” tegas Bissu Eka. Ajaran utama bissu adalah kesederhanaan.
Bissu Eka tak sungkan mengakui bahwa dirinya pun juga sudah melanggar aturan bissu sebenarnya. Pada masa lalu, bissu itu harus pakai sarung. Sekarang, sarung hanya dipakainya kala menggelar ritual. Poin utamanya, bissu menerapkan prinsip hidup sederhana.
Lalu kenapa bissu tidak ikut bersaing dalam politik? “Bissu ndak sampai berpikiran ke situ, karena bissu itu hidup untuk makan, makan untuk hidup,” kata Bissu Eka.
Atas alasan itu pula, dia tak pernah mendapat tawaran oleh calon anggota legislatif (caleg). Pun dari calon kepala daerah. Apa pun iming-iming mereka, bissu tak akan mudah terpengaruh.
“Kalau soal janji caleg, entahlah, karena saya tidak terima itu. Saya independen. Mau bawa-bawa uang (serangan fajar, red), tidak usah. Saya juga punya uang,” tegas Bissu Eka.
Prinsip lain yang mereka terapkan adalah “buta” dan “tuli”. Mereka menganggap diri buta kala melihat sesuatu yang tidak baik, dan tuli kala mendengar kalimat negatif.
“Jangan sepenuhnya percaya dengan janji-janji. Itu sudah disebut dalam Lontarak (kitab lampau Bugis-Makassar). Tak akan kumakan makanan yang berbau haram. Saya tidak mau menjadi orang yang kolusi korupsi dan nepotisme,” katanya.
“Kita memang untuk caleg-caleg, tertutup, karena kita tidak terlalu bisa mengenal dunia moderen,” sambungnya.
Ramalan Islam
Bissu pula yang menyampaikan aksara, termasuk ka-ga-nga-ka, pa-ba-ma-pa-, ca-ja-nya-ca, ya-ra-la, wa-sa-a-ha. Mereka langsung menerima ilmu dari dewata.
“Makanya di bissu itu ada rekko ota (lipatan sirih). Ada rekko paluttu, rekko alepu, rekko puco, dan sebagainya,” papar Bissu Eka.
Rekko paluttu disebut sebagai kendaraan Batara Guru dari dunia tengah ke dunia atas, lalu kembali ke dunia tengah. “Sekarang itu mungkin kayak israkmikraj, tapi dulu itu bissu adalah pendeta agama Bugis kuno,” urainya.
Jauh sebelum masuknya Islam di tanah Bugis-Makassar, bissu sudah ada. Mereka sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti ada agama terakhir yang akan datang, yaitu Islam.
Sebelum orang mengenal sembahyang (salat), bissu sudah tahu waktu-waktu salat. Ada lima waktu peribadahan wajib yang sudah ada sejak zaman bissu. Bissu Eka lalu mendetailkannya.
“Assurengna saddanna ganrange” alias pukulan gendang itu ada namanya “makdenniari”, yang berarti Subuh. Lalu ada “maktangesso”, yakni Zuhur. Selanjutnya “makarueng”, yakni Ashar. Kemudian “malabukesso”, Magrib. Terakhir “tengngabenni” alias Isya.
Sebelum orang-orang menemukan yang namanya “watakkale” (dalam diri), bissu itu sudah mewakili “watakklena di bosara seppulodua”. Ada 12 piring makan yang menjadi perwakilan dosa-dosa yang ada dalam tubuh bissu.
“Jadi yang tiga itu tadi, dari 1-2-3 sampai ‘siratu kurang seddi. Siratu kurang seddi’ itu berarti apa? Mungkin asmaul husna. Jadi ‘siratu kurang seddi’ itu ‘watakkale tottong puang alla taala’. Nyawa, tubuh, dan rahasia,” tambahnya.
Bissu juga mengenal konsep 3-3. Alam, misalnya, ada alam atas, tengah, bawah. Kehidupan juga tiga fase: rahim, dunia, akhirat. Tubuh pun tiga bagian besar: kaki, perut, kepala. Dalam membangun rumah, dibuat tiga bagian: ale bola, esso bola, dan rakkeang.
“Yang 12 itu perwakilan yang ada dalam tubuh kita. Dua tangan, dua kaki, satu kemaluan itu lima (totalnya). Dua lubang telinga, dua lubang hidung, dua mata, satu mulut (total tujuh). Itulah semua maladosa ri watakkalena,” kata Bissu Eka.
Jadi untuk menutupi kesalahan dan dosa, diperwakilkanlah itu di bosara sebagai persembahannya. “Jadi orang beranggapan bahwa itu musyrik. Ya, musyrik bagi orang yang tidak kenal, tapi kita ndak memuysrikkan,” tagasnya.
Karena selain makanan, itu pembelajaran juga buat anak bissu seperti bagaimana diajarkan sokko patangrupa, makanan/sajian empat rupa, berupa merah, kuning, putih, dan hitam. Itu artinya, bagaimana manusia mengenal empat unsur di dalam tubuh: tanah, api, angin, dan air.
Dahulu, bissu memang belum mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mereka sudah yakin dan percaya bahwa ada “dewata papunna sewa”, Datuk Patotoe. Artinya, mereka percaya bahwa ada kekuasaan yang sangat besar. Dalam konsep kekinian, kemudian dikenal dengan Yang Maha Kuasa.
Sebagai kelompok khusus, bissu mempunyai ilmu tinggi dalam tatanan adat istiadat Bugis. Mereka merupakan suri tauladan bagi orang banyak. Makanya, para raja pun selalu minta pendapat bissu ketika akan melakukan sesuatu atau ada persoalan yang membutuhkan kebijakan raja.
Bissu juga punya kitab, I Lagaligo dan Rangeng-rangeng Bissu. Berisi puji-pujian terhadap dewata. “Sekarang mungkin sama dengan barzanji atau zikir. Jadi bagaimana dalam kurun waktu tujuh hari itu mereka tidak berbuat maksiat. Mereka hanya puji-pujian,” terang Bissu Eka.

Beda Cara
Cara menjadi bisu beda-beda bagi tiap bissu. Masing-masing mendapat ilham dengan cara berbeda. Dalam ilmu bissu disebut “pammase”. Kedatangan “pammase” sangat beragam. Itu pula yang memengaruhi perbedaan gerakan (tari) bissu Segeri dan Bone.
“Gerakan bissu Segeri itu mengikuti ruh yang masuk ke dalam tubuh mereka. Leluhur siapa, jelmaan siapa yang merasuk dalam tubuhnya bissu itu,” kata Bissu Eka.
Sedangkan bissu di Bone ada keseragaman. Pammase datang sekaligus, langsung banyak. “Kalau di Segeri berbeda-beda karena tingkat ilmunya juga berbeda-beda. Cara menerimanya juga bermacam-macam,” imbuhnya.
Bissu Eka menegaskan, bissu bukan calabai (waria), calalai, perempuan, dan laki-laki. Bissu adalah satu identitas gender sendiri dalam peradaban Bugis. Karenanya, sejak dahulu, Bugis mengenal lima gender dalam relasi sosiokultural.
“Walaupun pada hakikatnya (bissu) terlahir sebagi laki-laki, setelah itu dinobatkan (menjadi bissu), lalu diperkenalkan dengan dewata (sebagai) perempuan, bukan dewata laki-laki,” sambungnya.
Calon bissu diperkenalkan dulu ke asal muasalnya, yakni terlahir sebagai laki-laki. Setelah itu, menjelma menjadi perempuan. Setelah jadi perempuan dan jauh dari maksiat, maka dinyatakan lolos. Di situlah calon bissu bisa dinobatkan menjadi bissu mapaccing (bissu sejati).
“Bissu itu sebenarnya bersih, mapaccing. Jadi bagaimana mengangkat jati dirinya di tengah masyarakat, dia jadi bisu. Karena di aturan bagaimanapun, norma adat bagaimanapun di tiga kerajaan terbesar Sulawesi Selatan, Tellupoccoe, dalam hal ini Bone, Gowa, Luwu, itu tidak membenarkan calabai dan calalai,” katanya.
Secara umum, tidak ada perempuan yang menjadi laki-laki, lalu menjadi bissu. Mayoritas, bissu berasal dari laki-laki, lalu bersifat perempuan, sebelum akhirnya menjadi bissu.
Memang ada satu bissu yang bermula dari perempuan, tetapi terjadi karena adanya “kesempurnaan”. “Bissu patappulo namanya, walaupun hitungannya 41. Ada satu (dari) perempuan namanya Bissu Poncong,” katanya.
Bagi bissu yang berangkat dari status perempuannya, proses masuknya tidak sama seperti bissu yang berasal dari laki-laki. “Gendernya lain. Dia baru bisa masuk bissu saat tidak haid lagi alias menopause, sebab bissu itu harus suci,” terang Bissu Eka.
Bissu Eka menegaskan pihaknya bukan LGBT. Bissu adalah entitas suci yang jauh dari kelakukan menyimpang. “Kita tidak seperti itu (LGBT), karena kita tidak maksiat, kita tidak berhubungan seks,” urainya.
Dia tak menampik, bissu selalu dipandang sebagai waria. Namun, jika memahami peran bissu, bissu bukan waria. Karenanya, bissu sangat jarang di-bully, beda halnya dengan waria.
“Bissu itu bagaimana mengangkat jati dirinya di tengah masyarakat, makanya kita jadi bissu. Kita beda dengan (oknum) calabai di sana yang genit dan menggoda. Banyak yang tidak tahu, tetapi itulah adanya istilah ‘mateppe’ (kepercayaan) karena adanya jiwa-jiwa ini,” tandas Bissu Eka.
Karena kharisma mereka, bissu tak pernah di-bully (diperundung). Mereka menganut filosofi, kala berjalan memelihara kaki dan saat bicara memelihara mulut.
Makin Kurang
Sejauh ini, tersisa tiga bissu senior di Segeri. Jika ada acara “maggiri”, pementasan khusus yang menampilkan kekebalan tubuh, bissu dari tempat lain yang ikut memeriahkan.
Minimal sekali setahun, para bissu Segeri mesti menggelar ritual. Salah satunya ritual pencucian benda arajang, dan doa tolak bala.
“Karena, kan, satu kali setahun berkumpul pada saat turun sawah (September), ada songkabala (tolak bala) setahun sekali dari komunitas bissu sendiri,” kata Bissu Eka.
Termasuk saat acara “mattompang arajang”, Bissu Eka dan kawan-kawan pasti ikut.
Menjaga Kesucian
Menjadi bissu bukan kemauan sendiri, melainkan pemberian. Apalagi, status itu membuat mereka harus terus menjaga kesucian. Karena bissu adalah satu entitas gender sendiri yang sangat terkait dengan teologi, mereka harus menjaganya.
Secara sosial, mereka tak pernah memilih jenis kelamin. Bahkan dengan status bissu itu, mereka sebenarnya terbebani. Tubuh mereka berbentuk laki-laki, namun hati dan perasaan mirip perempuan. Tak semua orang bisa membawa kondisi ini.
Akan tetapi, karena itu pemberian Tuhan, mereka pun tak pernah protes. Amanah bissu mesti mereka jalankan. Menjadi penjaga benteng kebudayaan dan nilai-nilai lampau Bugis.
“Saya sangat mensyukuri nikmat Tuhan yang dikasih,” kata Bissu Eka. Terlahir dengan fisik laki-laki, namun berhati perempuan tidak banyak dimiliki orang lain. Bissu menjadi pihak yang sangat bersyukur karena identitas-identitas parsial lintas gender ada dalam diri mereka.
Soal tudingan melawan kodrat, Bissu Eka menegaskan, dengan menerima takdir sebagai bissu adalah bentuk konsisten terhadap kodrat. Yang salah jika bissu melakukan hal-hal negatif, seperti mencuri, judi, berzinah, dll.
“Yang menyalahi kodrat kalau saya tidak mau menjalani ini,” katanya.
Ini juga sejalan dengan pernyataan Yusran dalam jurnal “Bissu Bukan Waria (Studi atas Hadis-hadis tentang Khuntsa)”. Dia mengatakan “Bissu hadir dalam masyarakat kerajaan Bugis sebagai sosok/makhluk yang suci, yang patuh dalam beragama dan tidak berpenyakit secara sosial atau seksual”.
Hal senanda disampaikan Titiek Suliyati, peneliti Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya dan Diploma III Kearsipan Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro Semarang dalam jurnalnya: “Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis”.
“Masyarakat Bugis tradisional menganggap Bissu sebagai kombinasi dari semua jenis gender tersebut, sejauh mereka menjalankan fungsi dan perannya di dalam masyarakat dengan baik. Masyarakat sering salah menafsirkan gender yang disandang Bissu, yang disamakan dengan calabai (banci). Masyarakat Bugis sangat menghormati Bissu, walaupun status gendernya tidak menunjukkan gender yang umum ada di lingkungan masyarakat.”
Politisi Berhati-hati
FAJAR berupaya mewawancarai sejumlah figur yang diebut-sebut akan maju pada Pilgub Sulsel 2024. Sayang, sebagian besar memilih sikap “hati-hati” dalam memberikan tanggapan dan pernyataan.
Mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memilih “no comment” ketika hendak diwawancarai mengenai LGBT plus. Demikian pula Moh Ramdhan Pomanto, Ilham Arief Sirajuddin, dan Andi Iwan Aras tak merespons permintaan wawancara FAJAR.
Sementara Taufan Pawe, mantan Wali Kota Parepare dua periode yang juga santer diisukan maju pada pilgub nanti, menghindari wawancara terkait bissu. Dua kali FAJAR meminta wawancara, namun Taufan belum bersedia.
Satu-satunya yang menanggapi adalah Indah Putri Indriani, salah seorang tokoh Sulsel yang namanya sering digadang-gadang akan maju pada Pilgub Sulsel 2024. Dia lebih melihat bissu sebagai bagian dari kebudayaan. Secara umum, dia menekankan pentingnya generasi muda diberi pemahaman akan kebudayaan daerah.
Indah memilih membahas kebudayaan Sulsel secara umum, yang di dalamnya ada bissu. Dia mengkaui, semua pihak mestinya mengambil peran dalam memperkenalkan kebudayaan ini kepada generasi penerus.
“Terkait bagaimana memperkenalkan budaya kepada generasi Z atau sebaliknya bagaimana generasi Z dan milenial ini tetap mengenal budayanya, ini memang pekerjaan rumah kita,” ujar Indah yang juga Bupati Luwu Utara dua periode itu.
Kekurangpahaman generasi muda terhadap budaya, bukan murni kesalah generasi milenial dan Z, melainkan juga ada tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat.
“(Tanggung jawab) itu ada di orang tua, kemudian di lingkungan sekolah, yang mungkin metode pengenalan literasi budaya ini yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman,” katanya.
Untuk melibatkan mereka, motode pengenalan mesti menggunakan pendekatan digitalisasi. Literasi tentang budaya tidak harus dengan cara yang hari ini kita gunakan. “Jadi sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mungkin dengan menggunakan artificial intelligent yang akrab dengan dengan generasi milenial,” papar Indah.
“Jadi terinternalisasi dalam dirinya. Walaupun dia tumbuh berkembang sesuai dengan zamannya, tetapi juga dia tidak melupakan dari mana dia berasal dan budaya apa yang yang membentuk orang tuanya sebenarnya”.
“Jadi harus tidak banyak menuntut dari generasi milenial sebenarnya, tetapi kita ini yang bertanggung jawab memperkenalkan budaya kepada mereka,” sambung perempuan bupati pertama di Sulsel itu.
Pantauan Medsos
Penulis berupaya menelusuri medsos tokoh-tokoh politik yang akan maju pada Pilgub Sulsel 2024 yang akan berlangsung November nanti. Di antara para figur itu, tak satu pun yang ditemukan pernah membuat unggahan yang terkait dengan bissu.
Ada sejumlah alasan hal itu terjadi. Pertama, bissu merupakan wilayah pinggiran yang tak memberi efek elektorat bagi figur politik. Dengan populasi bissu yang hanya hitungan jari, tentu bukan hal menarik bagi politisi untuk membuat atensi khusus bagi mereka.
Kedua, sikap berhati-hati. Ada stereotipe terhadap bissu, yang selalu dianggap bagian dari LGBT. Padahal, dalam sejumlah literatur, asumsi itu sangat tak berdasar. Bissu merupakan kelompok suci yang menjaga kesucian, sehingga tak boleh disebut kelompok yang menyimpang secara gender.
Para politisi menghidari disebut mendukung LGBT, padahal, sekali lagi, bissu bukan merupakan LGBT. Memang ada studi yang memasukkan mereka dalam kelompok LGBT plus, namun mereka merupakan kelompok spiritual tradisional yang jauh dari perilaku LGBT.
Ketiga, bissu tak signifikan bisa membawa pengaruh keterpilihan dalam pilkada. Karena itu, politisi akan cenderung mencari suara pada ruang padat dan dominan.
Sejarah Terputus
Nur Zakiatil Khashashah menatap bingung saat ditanya ihwal sejarah bissu. Jangankan melihat langsung, membaca tulisan tentang bissu pun ia tak pernah.
Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) angkatan 2021 itu bahkan baru tahu bahwa ada terminologi “bissu” saat ditanya oleh wartawan. Sebaliknya, dia yang bertanya balik.
“Memangnya apa bissu itu, Kak?” tanyanya dengan wajah bingung. Caca, panggilan akrab Nur Zakiatil Khashashah, baru sadar bahwa ada yang luput dalam pelajaran sejarah dan budaya selama ini. Bissu sebagai bagian integral kerajaan Sulawesi pada masa lampau, mestinya punya tempat dalam dunia pendidikan.
Banyak cara bisa dilakukan untuk melestarikan bissu. Menurut Caca, pementasan seni dan kebudayaan di dunia modern bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk itu.
“Harus ada event yang menampilkan mereka. Kalau perlu, harus sering ada pementasan tentang bissu. Dan kalau bisa bissu ini difilimkan,” saran mahasiswi kelahiran Belawa (Wajo), 1 November 2002 itu.
Hal serupa terjadi pada Dila Nurpadila. Mahasiswi Fakultas Psikologi UNM angkatan 2021 itu belum pernah menyaksikan langsung bissu. Namun, samar-samar ia mengingat pernah menonton di medsos terkait orang yang beratraksi menusuk lehernya dengan keris.
Video itu berlokasi di Bali. Rupanya, yang Dila maksudkan adalah tradisi “Ngurek” khas Bali. Memang ada kemiripan dengan tradisi bissu, namun yang ditonton itu bukan budaya khas Sulsel.
“Kalau yang tusuk-tusuk leher, dan kebal, kayaknya pernah lihat di TikTok. Tapi kalau istilah bissu, belum pernah dengar. Baru kali ini,” aku mahasiswi kelahiran Mandengeng (Gowa), 1 Juli 2023 itu.
Dila sadar dan khawatir. Jika generasi Z pada eranya saja tidak mengenal bissu, apalagi generasi selanjutnya. Karenanya sangat penting untuk melibatkan banyak pihak, membuat kebijakan yang bisa melestarikan bissu.
“Usul saya, bissu dimasukkan di pelajaran anak sekolah. Meskipun generasi kami dan yang akan datang tidak lagi mendapatkan (menyaksikan, red) bissu, setidaknya mereka tahu bahwa ada bagian kebudayaan kita yang bernama bissu,” saran Dila.
Pandangan Peneliti
Liputan ini juga mengangkat ihwal masih “miskinnya” gagasan para politikus, terutama calon kepala daerah dalam memberdayakan kaum bissu. Bissu sebagai penjaga dan benteng kebudayaan Sulsel, terus tersisihkan.
Keberadaan mereka sebagai pewaris masa lampau tak benar-benar mendapat tempat baik di tengah hegemoni kuasa saat ini. Apalagi dalam pemilu, alih-alih mendapat kontrak politik sebagai ikhtiar untuk mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi mereka, keberpihakan dari sektor politik pun masih sangat lemah.
“Bagi saya, saat ini bissu membutuhkan ruang yang aman dan juga nyaman dari stigma negatif dalam melaksanakan kegiatan ritualnya. Untuk itu, pemerintah baiknya hadir dalam proses menjaga komunitas bissu dalam melaksanakan kegiatan ritualnya. Dengan begitu, bissu sudah bisa terjamin dalam segala proses ritualnya,” usul peneliti bissu, Feby Triadi.
Agar bissu secara ideal terus eksis dan lestari, pekerjaan rumah ke depan adalah mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap mereka, tidak seperti saat ini, bissu sekadar pelengkap sejarah masa lalu. Hanya difungsikan sebagai kekayaan pariwisata semata, tanpa menyelami nilai-nilai yang mereka usung.
“Komitmen politikus hanya sebatas mencari atau menggalang suara. Komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi para bissu tidak begitu banyak. Sekiranya mereka bisa berkomitmen dalam kontrak politik yang transparan, mengenai bissu dan isu LGBT (itu akan lebih baik),” papar Feby.
Dari sisi hak-hak politik bissu saat ini dan dan hak-hak kewarganegaraan mereka, menurut Feby secara formal memang itu terpenuhi. Sama seperti warga biasa, mereka juga mendapatkan hak politik, seperti memilih, dan lain-lain, namun dalam pelaksanaan hak sebagai warga negara yang mendapat keadilan dalam berekspresi, seperti ritual dan upacara adat yang mereka percayai sendiri, itu masih kurang keberpihakan.
Di media (termasuk media sosial), tak pernah ada politikus yang berani menjanjikan hal-hal muluk terhadap bissu. “Hinggga saat ini belum ada yang saya dapatkan kasus seperti ini,” urai Feby.
Bissu memang jarang mendapat perundungan di dunia maya. Namun, stereotipe mereka dapatkan. “Saya hanya mendapatkan kasus para bissu dilihat dari stigma LGBT dari media sosial. Sehingga mereka seolah-olah tidak dilihat sebagai mahluk suci yang memiliki kelebihan, namun malah sebaliknya,” terang alumni Program Pascasarjana (PPs) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Selaku peneliti dan pengamat, Feby juga melihat ada situsasi memiriskan dalam kehidupan kaum bissu. Situasi paling miris itu adalah ada saja kelompok yang berkecimpung dalam komunitas budaya, menganggap mereka sebagai bagian dari gerakan LGBT. Padahal, ada kacamata lokal yang memiliki perspektif yang baiknya dilihat lebih mendalam lagi.
Dengan kondisi itu, bissu mestinya mendapat keberpihakan kebijakan. “Bissu harus dibijaki dalam perilaku kesehariannya dan juga dalam pelaksanaan upacaranya,” tandas Feby lagi.
Feby juga menuntut para anggota legislatif lebih mampu mendudukkan perspektif lokal terlebih dahulu,, lalu merumuskan kebijakan dari perspektif itu demi keberlanjutan bissu ke depan.
Apalagi, dalam konteks historis, mereka adalah bagian yang sangat penting terkait dengan suku Bugis. Selama aristokrat masih ingin mengakui dirinya sebagai arung, maka para bissu harus tetap berada dalam lingkaran kekuasaan.
Tradisi mengenai pemahaman lokal terhadap perlindungan kaum minoritas mesti ditanamkan lebih dalam lagi. (zuk)
Peliput: Ridwan Marzuki