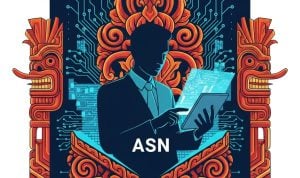Oleh: Nanda Yuniza Eviani
Legal Analyst di Law Firm Rudal & Partners
Di tengah semangat reformasi hukum pidana nasional, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) justru memperlihatkan gejala yang mengkhawatirkan: absennya partisipasi bermakna dari institusi penegak hukum yang paling terdampak, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski disusun untuk memperkuat sistem peradilan pidana, proses legislasi ini justru berjalan tanpa konsultasi substansial dengan lembaga yang akan menjadi pengguna langsung dari aturan-aturan baru tersebut. KPK sendiri telah menyampaikan bahwa mereka tidak dilibatkan secara resmi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP, dan baru mendapat ruang audiensi setelah berbagai keberatan muncul di ruang publik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah rancangan hukum acara pidana disusun dengan mengabaikan suara mereka yang sehari-hari berada di medan perangnya?
Secara kelembagaan, keberatan yang disuarakan KPK terhadap proses pembentukan RUU KUHAP tidak boleh dibaca sebagai ekspresi politik kelembagaan, apalagi sebagai bentuk resistensi terhadap otoritas legislatif. Ia lahir dari kebutuhan yang jauh lebih prinsipil dan fungsional: memastikan bahwa norma hukum acara pidana yang baru disusun tidak justru menghambat efektivitas kerja lembaga penegak hukum itu sendiri. KPK adalah entitas yang dibentuk dengan mandat konstitusional melalui koreksi terhadap sistem peradilan pidana, dan karena itu berada dalam posisi strategis: bukan sekadar sebagai pengguna hukum, tetapi sebagai pihak yang akan menguji kualitas hukum itu dalam praktik.
Sebagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sebuah kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime), KPK memiliki kepentingan langsung terhadap arsitektur hukum acara pidana nasional. Namun fakta menunjukkan bahwa hingga DIM RUU KUHAP ditandatangani Presiden dan diserahkan ke DPR pada 23 Juni 2025, tidak ada pelibatan resmi kepada KPK. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan lembaganya tidak pernah diundang dalam tahap awal pembahasan. Bahkan, 17 isu substansial yang telah disusun dalam kajian internal bersama para ahli hukum pidana, meliputi ketentuan penyitaan, pembatasan masa penahanan, penyidikan tindak pidana korporasi, hingga potensi tumpang tindih antar aparat penegak hukum, tidak pernah dibahas dalam forum resmi yang memungkinkan KPK menyampaikan posisi hukumnya secara argumentatif.
Barulah setelah sikap kritis KPK mendapat perhatian luas di ruang publik, wacana audiensi dengan DPR mengemuka. Tentu, respons Komisi III DPR yang menyatakan kesediaannya menerima masukan dari KPK patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan politik dan legislasi yang progresif. Namun hal itu tidak boleh mengaburkan satu kenyataan penting: keterbukaan yang datang terlambat tetap menyisakan luka konstitusional. Dalam pembentukan undang-undang, terutama yang menyangkut struktur kerja sistem peradilan pidana, waktu pelibatan sangat menentukan bobot partisipasi. Ketika substansi norma telah difinalisasi dalam DIM, ruang dengar berikutnya berisiko berubah menjadi validasi pasif. Bahkan kehilangan daya korektifnya.
Kritik ini bukan untuk menegasikan itikad baik DPR, melainkan untuk menegaskan bahwa makna partisipasi dalam pembentukan hukum bukan hanya siapa yang diundang, tetapi kapan dan dalam konteks apa ia dilibatkan. Demokrasi legislatif bukan hanya soal keterbukaan prosedur, tetapi tentang kualitas deliberasi substantif antar aktor negara. Persoalan ini harus dipandang bukan dari kacamata sektoral, melainkan dari perspektif sistemik, bahwa penyusunan hukum acara pidana tanpa dialog setara dengan lembaga penegak hukum akan membuka celah disonansi antara norma dan pelaksanaan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di lapangan.
Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan undang-undang bukan semata peristiwa legal-formal antara dua cabang kekuasaan—legislatif dan eksekutif. Ia merupakan pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Maka dari itu, proses legislasi harus tunduk pada asas demokratis, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menegaskan bahwa meaningful participation adalah bagian integral dari konstitusionalitas produk legislasi. Partisipasi yang sah bukanlah soal kehadiran fisik semata, melainkan soal sejauh mana masukan tersebut diberi ruang pengaruh dalam substansi norma.
Dalam konteks RUU KUHAP, KPK bukan sekadar lembaga teknis pelaksana, melainkan institusi negara independen yang bekerja dalam rezim hukum acara lex specialis. UU No. 19 Tahun 2019 (revisi UU No. 30 Tahun 2002) memberi KPK kewenangan khusus dalam penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana korupsi. Kewenangan tersebut bukan hanya operasional, tetapi juga normatif: membentuk sistem kerja tersendiri yang hanya dapat diubah dengan mempertimbangkan karakteristik kekhususan itu. Prinsip lex specialis derogat legi generali menegaskan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan yang umum. Artinya, hukum acara pidana umum tidak bisa diberlakukan sembarangan untuk mempersempit ruang gerak lembaga seperti KPK.
Karena itu, ketika KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan norma hukum acara pidana umum, padahal norma itu berpotensi menggeser sistem khusus yang telah diatur dalam undang-undang sektoralnya, maka kita sedang mengabaikan prinsip dasar penataan norma dalam negara hukum. Menyusun KUHAP tanpa memperhitungkan posisi lex specialis lembaga seperti KPK bukan hanya keliru secara teknis, tetapi patut diduga cacat secara sistemik. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas legitimasi normatif KUHAP, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik antar norma, ketidakpastian hukum, dan disonansi dalam pelaksanaan hukum pidana ke depan.
Lebih dari itu, sistem checks and balances dalam desain ketatanegaraan Indonesia tidak berhenti pada pemisahan cabang kekuasaan secara vertikal, tetapi juga melibatkan fungsi pengawasan horizontal antar lembaga negara. Dalam konteks ini, KPK bukan kompetitor kekuasaan legislasi, melainkan bagian dari arsitektur negara hukum yang bertugas mengawal kualitas pelaksanaan hukum pidana secara independen. Mengesampingkan KPK dalam pembentukan norma yang menyentuh langsung kewenangannya berarti menutup mekanisme korektif yang semestinya dijaga dalam proses pembentukan hukum. Norma hukum yang lahir tanpa menyentuh realitas operasional institusional akan kehilangan sensitivitas konstitusionalnya. Karena hukum yang lahir tanpa ruang koreksi, hanya akan tumbuh menjadi sistem yang lupa siapa yang seharusnya ia layani. (*)