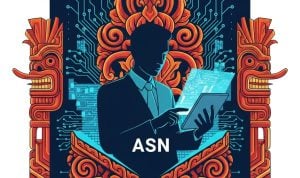Oleh: Ipa Bahya
Alumni Sastra UGM
Di balik tawa dan absurditasnya, “Jodoh 3 Bujang” adalah film yang secara berani menyorot wajah budaya Bugis-Makassar—terutama satu aspek yang sering tak terbantahkan, tak bisa ditawar, dan dalam banyak kasus, tak bisa ditanggung: uang panai.
Film ini mengangkat bagaimana sebuah tradisi yang semula lahir sebagai bentuk penghormatan, perlahan bergeser maknanya ketika nominal lebih diutamakan daripada niat. Dalam konteks pernikahan adat Bugis, uang panai adalah harga yang harus dibayar calon mempelai pria untuk mendapatkan restu dan martabat dari keluarga calon istri. Tapi, harga itu sering kali tumbuh melampaui nalar, menjelma menjadi syarat status sosial, bahkan alat ukur seberapa layak cinta seseorang diterima.
Disutradarai oleh Arfan Sabran—seorang sineas yang dikenal lewat karya dokumenter reflektifnya—“Jodoh 3 Bujang” menempuh jalur yang tak banyak berani dilalui film Indonesia: ia membongkar ketegangan antara nilai leluhur dan kebebasan individu, antara kebanggaan budaya dan tekanan sistemik yang membungkam.
Cerita berpusat pada tiga bersaudara—Fadly, Kifly, dan Ahmad—yang terjebak dalam rencana pernikahan massal yang diatur keluarga, demi alasan efisiensi. Di balik keputusan yang terdengar praktis itu, terselip tekanan ekonomi, ekspektasi sosial, dan tentu saja: negosiasi uang panai yang membengkak, tak hanya secara materi, tapi juga secara emosional.
Fadly, salah satu dari mereka, mencintai Nisa—perempuan Bugis cerdas dan mandiri. Namun cintanya harus berhadapan dengan tembok tradisi. Nisa dijodohkan dengan pria mapan, karena orang tuanya tak yakin Fadly mampu “membayar harga” yang pantas. Bagi mereka, cinta tak cukup. Yang penting: gengsi keluarga harus terjaga.
Melalui karakter Nisa, film ini menyorot beban ganda yang kerap ditanggung perempuan dalam masyarakat patriarkal yang berbalut adat: menjadi simbol kehormatan keluarga sekaligus objek transaksi sosial. “Cinta yang tulus, buat aku pribadi, mungkin sesuatu yang tidak dinilai dengan angka,” ujar Maizura, pemeran Nisa, dalam gala premier. Kalimat yang tampak sederhana itu sebenarnya menusuk akar dari masalah struktural yang ingin dibongkar film ini.
“Jodoh 3 Bujang” tidak menyerang tradisi. Ia justru memeluknya, lalu bertanya dengan jujur: apakah kita masih ingat alasan tradisi itu lahir? Bukankah uang panai semestinya bentuk penghargaan, bukan penghalang cinta? Bukankah restu seharusnya lahir dari cinta dan pengertian, bukan dari nominal yang diajukan dan disepakati?
Arfan Sabran menghadirkan dilema ini dalam balutan komedi yang jenaka, hangat, dan sangat manusiawi. Ia tak membuat film yang menggurui, tapi mengundang dialog—antara anak dan orang tua, antara masyarakat dan nilai-nilai yang mereka warisi. Humor yang ditawarkan bukan semata lucu-lucuan, tapi cara cerdas untuk menghindari sikap menghakimi. Karena pada akhirnya, yang dikritik bukanlah budaya itu sendiri, melainkan bagaimana kita memaknainya di masa kini.
Dengan setting lokal yang autentik, bahasa Bugis-Makassar yang hidup, serta konflik yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, “Jodoh 3 Bujang” menjelma menjadi cermin sosial yang jenaka namun tajam. Ia menyuguhkan bagaimana tradisi bisa menjadi alat pengikat sekaligus jerat. Dan di tengah dunia yang terus berubah, pertanyaan terbesarnya adalah: bagaimana kita tetap setia pada akar, tanpa mematahkan sayap generasi baru?
Film ini menjadi ruang kontemplasi bagi siapa pun yang sedang—atau pernah—berada dalam konflik antara cinta dan restu, antara logika dan adat, antara yang lama dan yang ingin diperbarui. Ia mengajak kita untuk tidak menolak tradisi, tapi memahami esensinya, lalu menjadikannya lebih manusiawi.
Karena pernikahan, pada akhirnya, bukan soal siapa membayar berapa. Tapi siapa yang benar-benar mau berjalan bersama—dalam cinta, pengertian, dan kebebasan yang sadar. (*/)