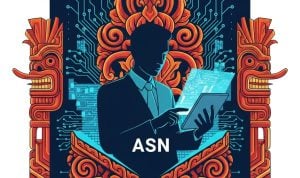Oleh: Herman
(Ketum SMPT IKIP Ujungpandang 97/98)
Rabu, 21 Mei 2025, bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah penanda sejarah yang mengusik ingatan kolektif generasi mahasiswa 1998—termasuk kami, para penggerak gerakan reformasi di Makassar.
Tepat 27 tahun lalu, jalanan bukan lagi ruang publik biasa, melainkan panggung aspirasi dan kemarahan intelektual. Di tengah hiruk pikuk itu, satu nama melekat kuat dalam ingatan: Yusuf Manggabarani, Kapoltabes Makassar kala itu.
Tegas, berwibawa, dan memiliki gaya komunikasi yang lebih mirip orator lapangan ketimbang aparat keamanan biasa. Kemarin, 20 Mei 2025 Beliau telah berpulang, meninggalkan sejumlah kenangan bagi kami mahasiswa Makassar Angkatan 98’.
Beliau bukan sekadar penegak hukum; beliau adalah “pendidik keras kepala” dalam dunia aksi. Bagi mahasiswa, beliau adalah sosok yang—dalam satu waktu—bisa membentak keras tapi juga mengulurkan solusi. Di hadapannya, kami sering “dicekoki” ceramah bernada tinggi, bukan karena beliau benci kami, tapi karena beliau (mungkin) ingin kami belajar: bahwa perjuangan bukan sekadar berteriak, tapi juga berstrategi.
Yusuf Manggabarani, orangnya tegas, kalau sedang marah lebih baik diam saja tapi jangan tinggalkan. Kalau sedang kesal, dengarkan saja ocehannya hingga mereda amarahnya baru bicara. Beliau enak diajak diskusi.
Setidaknya itu yang saya alamai ketika Beliau mejabat sebagai Kapoltabes Makassar 27 tahun yang lalu bertepatan dengan masa-masa reformasi kala itu. Selaku Ketua SMPT IKIP Ujungpandang saat itu lebih banyak bertugas di balik layar, yang di lapangan ada Iswari Al Farisi, Haris Cambang, Bongkar dan ketua-ketua senat fakultas. Bahkan saya selalu “disembunyikan” untuk tidak tanpak di kerumunan massa.
Tugas saya?, sederhana saja—katanya. Hanya memimpin rapat, menyusun strategi gerakan sebelum dan sesudah mahasiswa turun ke jalan. Tentu, itu bukan rapat biasa. Ini semacam pertemuan rahasia semi-militer, minus senjata, tapi penuh taktik dan daftar target yang harus digoyang dengan orasi.
Saya juga bertugas membangun komunikasi dengan para petinggi kampus—mereka yang lebih takut mahasiswanya turun ke jalan daripada kredibilitas kampus yang jatuh di mata penguasa. Jangan ditanya, ancaman DO kala itu bukan lagi wacana. Mahasiswa yang terlalu sering muncul di aksi demonstrasi, apalagi yang hobi pegang toa, tinggal tunggu saja keputusan pemecatan. Ibarat nasi yang tinggal ditanak.
Untuk urusan begini, saya sering harus bersitegang dengan PR III—wakil rektor yang tampaknya menganggap demo lebih berbahaya dari skripsi mahasiswa yang belum selesai. Tapi itu bagian dari paket lengkap: tak hanya melawan sistem, tapi juga negosiasi di lorong-lorong kekuasaan kampus.
Dan yang tak kalah penting (baca: melelahkan), adalah lobi ke aparat keamanan. Apalagi ketika suasana mulai panas—bukan karena cuaca, tapi karena mahasiswa dan ABRI (gabungan tentara dan polisi) sudah saling lempar tatapan yang tidak lagi akademis.
Kalau ada mahasiswa ditangkap, biasanya kami menginap semalam di kantor polisi. Dan di sinilah saya sering berinteraksi dengan Almarhum Bapak Yusuf Manggabarani. Beliau bukan hanya Kapoltabes, tapi juga “penguji lapangan” yang bisa membedakan mana mahasiswa idealis dan mana yang hanya ikut-ikutan supaya bisa bolos kuliah. Beliau bukan hanya orangnya tegas, tapi pada masa itu juga banyak mengedukasi – tepatnya mungkin memberikan latihan mental agar tidak mudah menyerah pada keadaan.
Pernah suatu ketika ada mahasiswa IKIP ditangkap. Seperti biasa, ini tugas saya untuk membebaskannya. Saya bersama dengan beberapa fungsionaris mahasiswa menghadap ke Beliau, yaaa….. diceramahi. Ceramahnya bukan menyejukkan dengan suara datar, tapi membentak dan dengan nada meninggi.
“Kalian tidak dilarang demo, tapi kalau merusak fasilitas umum, kalian berhadapan dengan polisi”, sambil menunjuki kami dengan tongkat komando dan nada suaranya meninggi.
Dalam hati saya bergumam, “Kalau tidak seperti itu bukan demo namaya Komandan tapi latihan baris-berbaris”. Kadang memang demo itu harus anarkis saat kita bersuara tapi tak didengar. Saat kekuasaan kita cubit tapi tak bergeming, di lambai tak melihat, maka harus ditampar supaya kaget.
Tapi, kami diam saja menunggu moment ini berlalu, hingga “ceramahnya” selesai. Baru kemudian diskusi berlanjut dan pada akhirnya kami diminta untuk buat surat penangguhan penahanan. Tapi kali ini lain, yang harus tanda tangan adalah petinggi kampus. Kamipun kembali bersitegang dengan Beliau.
Bagaimana mungkin petinggi kampus yang harus tanda tangan, sementara mahasiswa yang ditahan ini memang diinginkan oleh kampus untuk ditahan karena dia salah satu dari panglima gerakan yang sering turun ditugasi memimpin demonstrasi.
Tidak ada kompromi….
Kami pun saat itu juga buat surat penangguhan penahanan di atas kertas segel berlambang burung garuda. Lengkap dengan nama PR III IKIP Ujungpandang, kala itu Drs. H. Arifin Pasinringi (Almarhum semoga Allah merahmatinya). Kami tau Beliau tidak akan terima karena merasa ditodong. Soal todong menodong, ancam mengancam pada masa itu sudah biasa kami alami dengan petinggi kampus.
Situasi ini sudah kami antisipasi. Sebelumnya saya sudah bilang pada teman, “Kalau ada kondisi sebentar dimana saya harus keluar ruangan tanpa pamit, jangan panik. Kalian tetap tinggal, debat saja terus PR III sampai puas”.
Kalau saya sudah bilang begitu, teman yang lain sudah ma’fum. Ada rencana dan strategi yang tidak semua orang harus tau.
Tiba di kampus Gunung Sari Pettarani – di ruangan PR III. …… Benar saja, kami disambut dengan tidak bersahabat. Rupanya soal surat penangguhan penahanan lebih duluan sampai di ruangannya daripada fisik kami tiba di sana. Informasi dari polisi lebih cepat duluan tiba di meja PR III ketimbang kami yang minta untuk menandatangani surat penagguhan penahanan itu.
Prediksi kami benar—PR III meledak marah begitu surat penangguhan disodorkan. Tanpa menunggu konser omelan selesai, saya berdiri, mengambil kembali map surat itu, dan keluar ruangan tanpa sepatah kata. Bukan kurang ajar, tapi ini strategi: perang psikologi gaya mahasiswa dengan petinggi kampus.
Saya sendiri menuju Kampus Parangtambung untuk ketemu PD III FPBS Prof. Sugira Wahid (Almarhumah semoga Allah merahmatinya). Orangnya keibuan sering menasehati kami anak-anaknya yang nakal-nakal. Meskipun kami anak “nakal”, Beliau sayang sama kami. Beliau tidak pernah melarang kami demo tapi selalu menasehati – yang intinya sebenarnya juga melarang tapi dengan cara yang lain.
Baru saja saya buka pintu ruangannya dan salam, beliau terlihat telponan seseorang. Saya hanya dapat kode untuk duduk di sofa ruangan beliau. Dari pembicaraannya yang saya tangkap, Beliau telponan dengan PR III. Kadang suaranya tegas dan sedikit menasehati kadang juga diam mendengar. Saya tidak tau apa yang diomongkan PR III, tapi arah pembicaraannya soal mahasiswa FPBS yang ditahan di Poltabes dan demo-demo yang dilakukan mahasiswa yang dimotori pengurus senat. Terdengar pula nama saya disebut-sebut.
“Mana surat itu, sini saya tandatangani”, serunya menutup gagang telpon, sambil mengomeli PR III yang tidak mau tandatangan.
Sebenarnya saya baru mau jelaskan, tapi PR III sudah jauh menjelaskan lewat telpon untuk tidak memberi ruang menandatangi surat penangguhan penahanan itu. Tapi respon PD III malah sebaliknya.
Di rumah dinas Pak Yusuf Manggabarani, kami serahkan dokumen itu dengan hati yang setengah lega, setengah waswas. Beliau menerimanya tanpa banyak kata, membaca pelan, dan sejenak suasana menjadi hening—bukan karena tegang, tapi karena kami tahu, ini bukan sekadar soal tanda tangan, tapi soal kepercayaan. Di ruangan sederhana itulah kami melihat sisi lain dari seorang Yusuf Manggabarani—bukan hanya sebagai aparat yang bertugas menjaga ketertiban, tapi juga sebagai manusia yang diam-diam memahami keresahan anak muda yang sedang belajar menyuarakan nurani.
Beliau tidak selalu setuju dengan kami, bahkan sering kali marah dan menyentil keras. Tapi dari semua itu kami sadar, kemarahannya bukan karena benci—melainkan bentuk didikan. Di balik tongkat komando dan suara tinggi itu, ada sosok yang sedang mengajarkan kami tentang tanggung jawab, tentang keberanian yang tak cukup hanya dengan berteriak, tapi juga harus disertai keteguhan hati saat konsekuensi datang mengetuk pintu.
Saat itu kami satu hal penting: bahwa perjuangan tidak hanya ditakar dari seberapa keras kita melawan, tapi juga dari seberapa dalam kita dipahami, bahkan oleh mereka yang kita anggap sebagai lawan. Hari-hari itu adalah masa pendidikan informal terbaik. Kami belajar berpolitik, berdiplomasi, membaca suasana, bahkan sedikit “berteater”. Di situlah kami mengenal Pak Yusuf bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai pribadi. Tegas, keras, namun tidak menutup ruang dialog.
Kini beliau telah tiada. Tapi kenangan itu tetap hidup. Tongkat komando yang dulu menunjuk-nunjuk itu kini hanya tinggal simbol. Namun pelajarannya abadi: kekuasaan harus dikritik, tapi kritik pun perlu dibangun di atas nalar dan strategi. Dan demo? Demo itu bukan tujuan. Ia hanya alat. Alat untuk menyadarkan, menggugah, dan kadang… menampar.
Semoga Allah merahmati beliau—dan semua tokoh-tokoh kampus masa itu—yang secara sadar atau tidak, telah membentuk generasi yang tak hanya berani melawan, tapi juga tahu kapan harus diam dan berpikir. (*)
Makassar, 21 Mei 2025