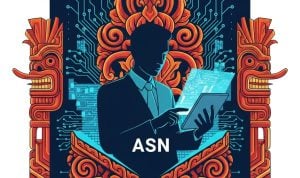Oleh: Dr Muhammad Asdar / Akademisi UNIFA
Tulisan ini terinspirasi setelah membaca analisa seorang pakar ekonomi politik Prof Vedi Hadiz dari University of Melbourne Australia, tentang menakar dinasti politik langgengkan kekuasaan dan bersirkulasi hanya di kalangan elite, dikutip Jumat (17/11/2023).
Tercengang, begitu saya membaca tulisan ini. Miris memang, ketika kejadian praktik pelanggaran etik, politik dinasti, hingga nepotisme hanya beredar (sirkulasi) di kalangan para elite.
Dalam teori politik dan sosiologi kata Elite adalah sekelompok kecil orang-orang yang berkuasa, misalnya oligarki yang menguasai kekayaan dan kekuasaan politik dalam masyarakat.
Masyarakat pun seolah sudah terbiasa dengan praktik tersebut di tingkat lokal. Misalnya, ketika kepala kampung/desa dijabat turun menurun oleh satu rumpun keluarga.
Ketika ditanya salah-nya dimana? Apakah kaum terpelajar dan kampus gagal melahirkan dan menghimpun ide politik kepada masyarakat? Atau pemerintah tidak serius memberikan edukasi politik melalui lembaga penyelenggara pemilu? Jawabannya kembali kepada kita semua.
Menurut penulis ada 3 alasan yang perlu dicermati ketika masyarakat antipati terhadap persoalan moral, KKN, dan pelanggaran etik menjadi hal yang biasa-biasa saja.
Pertama, bagi masyarakat persoalan pelanggaran etik dan politik dinasti hanya menguntungkan beberapa pihak ditingkatkan elite penguasa dan pengusaha dan tidak berbanding lurus dengan persoalan substansi yakni persoalan hidup dan kehidupan. Mereka menganggap lebih penting berdaya mencari nafkah sehari-hari untuk sesuap nasi demi keluarga tercinta. Daripada sibuk mengurusi dan memikirkan para elite yang setelah “pesta demokrasi” kembali ke fase adem ayem demi kepentingan kelompok/golongan tertentu.
Kedua, diawal gagalnya perencanaan lembaga legislatif, yudikatif hingga eksekutif (pemerintah) untuk mengentaskan peraturan dan pencegahan politik dinasti karena faktor kepentingan sesaat. Jauh sebelum pemerintahan modern berlaku, masyarakat sudah terbiasa dipimpin secara turun temurun melalui satu keluarga/kerabat.
Ketiga, pers sebagai pilar keempat demokrasi yang juga berfungsi sebagai kontrol sosial masih dianggap kurang mempersuasi masyarakat melalui program berdemokrasi yang kuat dan sehat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini didasarkan pada stigma dan hegemoni media sebagai industri dan institusi.
Maka, jangan heran kondisi ini akan terus berulang pada pemilu berikutnya bila fakta tersebut diatas tidak mendapat perhatian serius semua pihak.
Benar apa yang diramalkan Francis Fukuyama penulis buku the great distruption/guncangan besar (1999) bahwa untuk melihat tatanan dan struktur sosial masyarakat dan kemajuan pendidikan politik suatu negara maka lihatlah apa yang dilakukan (penguasa) hari ini. Bila, kepercayaan menipis dan individualisme mengalahkan komunitas maka jangan mengira diamnya masyarakat terhadap grasak-grusuk politik di tingkat elite akan menjadi modal utama dalam memilih pemimpin di masa mendatang. Mereka pasti punya pilihan sendiri tanpa dimobilisasi karena Ia yakin mau melihat keberlangsungan demokrasi di negeri yang mereka cintai Indonesia.
Lalu, pantaskah kita berputar diwilayah saling mengklaim pembenaran disaat masyarakat yang menjadi obyek tidak begitu berharap adanya saling bermanuver politik pada wilayah medium hingga top leader. Mereka masyarakat bawah (grassroot) hanya butuh kepastian ekonomi, hukum, dan stabilitas negara menjadi aman-aman saja ketika sibuk bekerja dan berusaha.
Dan pada akhirnya suara kebatinan rakyat akan berpihak kepada calon pemimpin yang ikhlas bekerja, memastikan roda kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan serta taat terhadap perilaku yang pancasilais dan tindakan sesuai dengan peraturan.
Padahal, roh reformasi yang digaungkan 1998 harusnya para elite sadar bahwa perjuangan para aktivis yang telah menginisiasi lalu menginstalisasi demokrasi kemudian berkonsolidasi untuk menata kemajuan demokrasi Indonesia lebih baik dari sebelumnya.
Lantas, siapa yang akan mereka pilih pada Pemilu 14 Pebruari 2024 mendatang. Jawabnya singkat mereka memilih karena apa yang mereka lihat, rasakan, dan pikirkan dan tidak hanya karena kebaikan. Karena orang baik belum tentu suci, dan orang suci tidak ada jaminan masuk surga. Jadi para calon pemimpin bangsa mari perbaiki niat membangun Indonesia. (*)