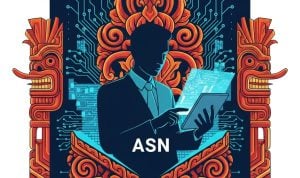Oleh : Asratillah
(Direktur Profetik Institute)
Dekat penghujung Juli 2025, suasana sejumlah kampus di Makassar mendadak mencekam. Bukan karena isu kenaikan UKT atau pembekuan organisasi mahasiswa, tetapi oleh kehadiran sekelompok orang tak dikenal yang menyatroni beberapa kampus dengan membawa busur panah dan senjata tajam. Mereka berteriak mencari “orang Palopo,” memasang spanduk bernada ancaman, dan meninggalkan ketakutan. Aksi yang lebih menyerupai teror ini menjadi pertanda bahwa kampus, yang seharusnya menjadi rumah tumbuh kembangnya gagasan, telah berubah menjadi arena pertarungan identitas.
Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Mengapa kekerasan di antara mahasiswa terus berulang? Dan bagaimana kita, sebagai warga kota, memahami kekerasan yang berulang ini dengan lebih jernih?
Kita bisa mencoba menelusuri fenomena ini bukan sebagai insiden yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari konstruksi sosial yang lebih dalam. Dengan meninjau kejadian-kejadian serupa di Makassar dalam lima tahun terakhir, dan menafsirnya melalui lensa teoritik semisal teori Ralf Dahrendorf dan Pierre Bourdieu, kita dapat melihat bahwa konflik ini bukan hanya soal siapa yang menyerang siapa, tetapi tentang bagaimana kuasa, identitas, dan simbol dipertarungkan dalam arena yang bernama kampus.
Insiden Juli 2025: Gejala Lama dalam Kemasan Baru
Di kota ini, kekerasan mahasiswa seakan menjadi rutinitas tahunan. Tahun 2020, kita mendengar kabar bentrokan antar fakultas di UNM, berawal dari hal sepele yang berubah menjadi trauma kolektif. Di UMI, setiap tahun seolah ada saja gesekan antar kelompok mahasiswa yang menanggalkan perbedaan fakultas dan justru memunculkan garis identitas lain—asal daerah, misalnya.
Tahun 2024, kampus menjadi arena protes besar dalam gelombang #ReformasiDikorupsi. Jalan-jalan Makassar penuh demonstran muda, sebagian dari mereka kemudian terlibat bentrokan dengan aparat. Semua ini membentuk lanskap emosional kampus yang mudah terbakar. Dan kini, 2025, kita tidak hanya menyaksikan konflik antar kelompok, tetapi juga tindakan yang menyerupai teror: orang-orang bertopeng, bersenjata tajam, mencari “orang Palopo”.
Mungkin inilah titik balik: saat kekerasan tak lagi menjadi efek benturan spontan, tapi menjadi bagian dari narasi. Ia punya pesan, punya simbol, dan ia menyasar identitas.
Aksi pada 24 Juli 2025 bukan cuma soal perkelahian. Ada semacam “drama sosial” yang ingin dipertontonkan. Para pelaku membawa spanduk ancaman, meneriakkan pertanyaan provokatif, seolah ingin mempermalukan bukan hanya individu, tetapi seluruh identitas komunal. Spanduk yang digantung di pagar kampus tidak bicara kepada korban, tapi kepada publik: lihat, kami bisa menguasai ruang ini.
Namun, apakah benar ini hanya soal salah paham antar mahasiswa? Atau ada sesuatu yang lebih struktural yang membuat kekerasan semacam ini terusberulang?
Konflik dan Sumbu Ketegangan Otoritas
Barangkali kampus terlalu lama kita bayangkan sebagai ruang steril. Sebuah tempat belajar, tempat mahasiswa mengutip teori dan bersiap menyusun skripsi. Tapi siapa sangka, justru di balik tembok institusi itu, konflik sosial menari-nari. Ralf Dahrendorf, dengan dingin dan tenang, pernah mengingatkan: masyarakat itu bukan harmoni, melainkan gesekan. Bukan keseimbangan, tapi pertarungan. Dan kampus, meski bercat putih, kelas ditata rapi dan berpagar tinggi, tetaplah bagian dari masyarakat. Kampus tak luput dari pelbagai bentuk gesekan.
Konflik yang pecah di Makassar akhir Juli 2025 adalah pentas paling nyata dari apa yang Dahrendorf sebut sebagai pertarungan otoritas. Sejumlah orang tak dikenal masuk ke kampus—tak diundang, tak tercatat, tapi membawa panah dan spanduk ancaman. Mereka menantang. Dan yang lebih mengganggu bukan hanya kehadiran fisiknya, tetapi pesan simbolik yang mereka tinggalkan: bahwa kekuasaan bisa direbut, bahkan dari tangan rektorat sendiri.
Kita diajak menyaksikan bagaimana otoritas formal—rektor, satpam kampus, bahkan statuta—ditarik mundur oleh sekelompok kecil aktor yang tampil bak pengatur lakon. Mereka bukan sekadar membawa senjata tajam, tetapi membawa simbol: dominasi, kendali, intimidasi. Dan itu cukup membuat kampus kehilangan suara. Dalam terminologi Dahrendorf, inilah wajah masyarakat yang tak lagi berjalan dalam konsensus, melainkan sedang dikuasai oleh konflik terbuka.
Kampus menjadi arena di mana otoritas tidak lagi dipegang oleh struktur, melainkan oleh siapa yang paling lantang dan paling ditakuti. Ketua organisasi, senior lama, kelompok daerah—semuanya menjadi titik-titik panas (hot spot) dalam kontestasi otoritatif. Otoritas, bagi Dahrendorf, bukan soal karakter seseorang, tapi soal posisi yang memungkinkan dominasi. Maka tak heran, jika kursi organisasi diperebutkan, sekretariat dijaga bergantian, dan “angkatan lama” terus-menerus mengingatkan siapa yang layak bicara dan siapa yang harus diam.
Apa yang menarik dari pendekatan Dahrendorf ialah bagaimana ia menempatkan konflik sebagai pemicu terbentuknya kelas sosial baru. Bukan proletar dan borjuis dalam arti klasik, melainkan pembeda baru: mereka yang memiliki legitimasi simbolik dan mereka yang hanya menjadi penonton dalam pertunjukan kampus. Organisasi daerah, dengan segala romantismenya, menjadi kendaraan. Mereka menyusun ulang lanskap otoritas, membentuk aliansi, dan menciptakan garis batas antara yang “dulu datang lebih dulu” dan “yang harus tahu diri”.
Namun jangan buru-buru menilai konflik ini destruktif semata. Dalam kaca mata Dahrendorf, konflik bisa jadi momen emansipasi. Ia menggugah, meskipun kadang dengan luka. Ia menendang bangku tua tempat elite lama duduk nyaman, dan membuka pintu bagi pembicaraan baru. Mungkin, dari benturan ini kita dipaksa untuk meninjau ulang bagaimana kampus mendistribusikan kekuasaan. Siapa yang selalu tampil mewakili? Siapa yang selalu bicara di mikrofon? Siapa yang tak pernah diberi ruang di forum-forum pengambilan keputusan?
Konflik di Makassar memperlihatkan bahwa tidak adanya lembaga mediasi yang kredibel hanya akan memaksa konflik bergerak dalam bentuk paling kasar. Tidak ada dialog yang memadai, maka busur menjadi bahasa. Tidak ada representasi yang inklusif, maka spanduk ancaman menggantikan forum. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bukan bagaimana meredam konflik, melainkan bagaimana membuat konflik bisa ditanggung bersama—diolah, dimaknai, diselesaikan tanpa darah atau stigma.
Dahrendorf, pada akhirnya, menyodorkan cara pandang yang membuat kita tidak lagi melihat konflik sebagai aib kampus. Tapi sebagai cermin. Dan mungkin juga sebagai pintu. Menuju kampus yang lebih adil, lebih jujur, dan tidak lagi menyimpan kekuasaan hanya di balik map organisasi atau dalam logat mayoritas.
Habitus Kekerasan dan Modal Simbolik Kampus
Tidak semua kekerasan datang dari amarah. Ada yang lahir dari warisan. Dari cara melihat dunia yang ditanamkan sejak hari pertama seorang mahasiswa menjejakkan kaki di kampus: bahwa ini bukan sekadar tempat belajar, tapi juga medan pertarungan. Pierre Bourdieu menyebutnya habitus—cara berpikir dan bertindak yang terbentuk lama sebelum kita sadar telah mengadopsinya. Ia tidak lahir dari kehendak bebas sepenuhnya, melainkan dari kebiasaan yang diwariskan, dari cerita-cerita senior, dari simbol-simbol yang mengisi dinding sekretariat organisasi.
Habitus kekerasan tumbuh dari ruang sosial yang menjadikan konflik sebagai alat negosiasi eksistensi. Di banyak kampus di Makassar, cerita soal siapa yang pernah diserang siapa, siapa yang harus dibalas, dan bagaimana cara menjaga nama baik organisasi bukan sekadar dongeng masa lalu, tapi doktrin. Dan yang lebih rumit: semua itu terasa wajar. Karena ia tidak tampil dalam bentuk kekerasan murni, tetapi dibungkus dengan bahasa kehormatan, harga diri, dan solidaritas.
Kampus, bukan panggung kosong. Ia adalah arena. Tempat di mana aktor saling bersaing membawa modal: sosial, kultural, ekonomi, hingga simbolik. Modal simbolik—itulah mata uang paling berharga. Nama baik, pengaruh tak tertulis, hak bicara yang tidak tercatat dalam AD/ART, tapi diakui oleh semua. Organisasi dengan modal simbolik tinggi tidak perlu berteriak, karena diamnya pun bisa menggoyang.
Maka ketika modal itu terancam, responsnya bukan hanya administrasi internal. Ia bisa berubah menjadi selebaran ancaman, spanduk perang, hingga kehadiran orang bertopeng membawa busur. Karena di balik aksi kekerasan itu ada pesan simbolik: bahwa dominasi sedang dipertaruhkan. Arena kampus sedang diguncang, dan siapa pun bisa naik ke atas panggung, asalkan tahu naskahnya.
Spanduk yang dibentangkan, teriakan mencari “orang Palopo”, bukan sekadar provokasi. Ia adalah upaya untuk mengatur ulang struktur simbolik kampus. Untuk mendefinisikan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus angkat kaki. Dalam kacamata Bourdieu, ini bukan anarki. Ini adalah logika arena yang dijalankan secara ekstrem.
Yang membuat semuanya semakin kompleks adalah kemampuan kekerasan simbolik untuk menyamar sebagai kepatutan. Banyak dari mereka yang terlibat bahkan tidak merasa sedang melakukan kekerasan. Mereka merasa sedang menjalankan mandat tak tertulis. Karena dalam habitus mereka, membalas adalah kewajiban, menyerang adalah bentuk loyalitas, dan menang adalah kehormatan.
Dan institusi kampus? Terlalu sering membiarkan arena ini diatur oleh logika internal masing-masing kelompok. Alih-alih menjadi fasilitator atau penengah, kampus kerap menjadi penonton yang hanya turun tangan ketika berita sudah sampai ke media. Sanksi dijatuhkan, surat edaran dikeluarkan, lalu kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi habitus tetap hidup. Ia tidak pernah benar-benar dibongkar. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menyala kembali.
Solusinya tidak sederhana. Tapi jelas, kita tidak bisa hanya memperbanyak satpam atau membatasi aktivitas organisasi. Yang dibutuhkan adalah transformasi. Habitus kekerasan harus digantikan dengan habitus dialogis. Modal simbolik yang mengancam harus digantikan dengan simbol kolektif yang menyatukan. Kampus harus belajar menjadi arena yang sehat: tempat orang berbeda bisa duduk satu meja tanpa saling mencurigai asal-usul.
Karena konflik yang kita lihat hari ini, bukan sekadar urusan mahasiswa. Ia adalah cermin dari bagaimana kampus—dan masyarakat kita secara umum—membiarkan kekuasaan simbolik bekerja tanpa kendali. Dan jika kita ingin memperbaikinya, kita harus mulai dari cara kita memaknai simbol, cara kita bercerita, dan cara kita mengingat siapa yang pernah berkuasa atas siapa.
Kampus sebagai Arena Sosial: Perebutan Kuasa dan Representasi
Mari kita bayangkan kampus bukan sekadar tempat orang belajar, tetapi sebagai lanskap yang penuh bisik-bisik, saling tatap, dan ajakan-ajakan samar. Tempat di mana setiap ruang menyimpan tanda, dan setiap lorong bisa menjadi panggung. Di sinilah ide Bourdieu tentang “arena” menjadi sangat penting. Kampus adalah arena sosial—sebuah gelanggang—tempat para aktor membawa serta modalnya: entah itu keberanian, jejaring, sejarah, atau simbol.
Di Makassar, gelanggang ini penuh warna. Ada organisasi mahasiswa yang membawa bendera nasional, ada yang menjunjung nama daerah, dan semua berebut satu hal yang tak kasat mata: kuasa atas representasi. Mereka tak sekadar ingin eksis, tapi ingin diakui sebagai yang paling berhak bicara, paling layak didengar. Perebutan ini tidak selalu lewat debat atau pemilu organisasi. Kadang ia hadir dalam bentuk senyap—dalam siapa yang duduk di kursi tengah saat forum, siapa yang spanduknya boleh menempel paling lama, siapa yang diamnya cukup untuk membungkam.
Modal simbolik menjadi penentu dalam arena ini. Organisasi yang punya sejarah panjang akan lebih dihormati, meski tak selalu relevan. Yang baru muncul, harus pandai-pandai membaca situasi. Salah langkah, ia akan jadi bulan-bulanan bukan karena kesalahan ide, tetapi karena melanggar urutan yang tak tertulis. Seperti seorang aktor yang masuk ke panggung sebelum gilirannya, ia akan didorong keluar. Bukan karena buruk, tetapi karena dianggap belum waktunya.
Dan ketika waktu tak kunjung datang, sebagian memilih mengambilnya paksa. Maka kekerasan, dalam arena seperti ini, adalah pesan. Ia bukan semata bentuk agresi, tetapi cara berkata: kami juga ada, dan kami tak akan menunggu di pinggir.
Masalah menjadi rumit ketika wasit pertandingan, yakni institusi kampus, lebih sering absen atau pura-pura tidak melihat. Ketika otoritas tak mengatur, kekuasaan informal mengambil alih. Maka arena berubah menjadi gelanggang liar, tempat aturan digantikan oleh alur kekuatan: siapa yang punya suara keras, dialah yang menang.
Di tengah situasi ini, mahasiswa yang tidak punya jaringan atau tidak berasal dari kelompok dominan akan merasa gamang. Ia harus memilih: bergabung dan mengikuti aturan main yang tak pernah dituliskan, atau terus bertahan sambil menahan diri di pinggiran. Kampus pun, alih-alih menjadi ruang pembebasan, justru memelihara dominasi yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun seperti yang selalu ditawarkan oleh ide tentang arena: segala sesuatu bisa dipertarungkan ulang. Representasi tidak harus diwarisi. Ia bisa dibangun, dirundingkan, bahkan diciptakan kembali. Asal ada kemauan untuk merumuskan ulang makna hormat, makna pengaruh, dan makna siapa yang layak bicara.
Kampus bisa menjadi lebih dari sekadar tempat kuliah. Ia bisa menjadi ruang kemungkinan—jika semua aktor bersedia merobohkan panggung lama, dan bersama-sama membangun pentas yang tak lagi berpihak hanya pada mereka yang datang lebih dulu.
Menuju Reorientasi Identitas dan Regulasi Arena
Kekerasan mahasiswa bukanlah takdir, tapi juga bukan kebetulan. Ia adalah produk dari struktur sosial yang timpang, dari habitus yang keras, dan dari arena yang tak diatur dengan baik. Maka solusinya tidak cukup dengan polisi kampus atau sanksi administratif.
Kita perlu reorientasi: cara baru memahami identitas mahasiswa yang tak lagi didasarkan pada asal daerah atau loyalitas sempit. Kita perlu meregulasi ulang arena kampus: mendesain ulang organisasi mahasiswa, memberi ruang partisipasi yang adil, dan menghentikan privilese simbolik yang diwariskan semata karena sejarah.
Dan yang terpenting, kita perlu mengembalikan kampus sebagai ruang belajar: tempat berdebat tanpa takut, tempat berbeda tanpa dicurigai, dan tempat semua bisa tumbuh tanpa harus saling melukai. (*)