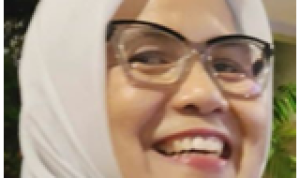Oleh: Satria Karsa Purwanegara
Mahasiswa Program Magister Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Cempalagi atau biasa penduduk sekitar menyebutnya Bulu Cempalagi yang terletak di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah gua yang senyap dan tak banyak disebut dalam buku sejarah. Gua itu bernama Gua Janji, atau Gua Janci menurut lidah lokal. Ia terletak di perbukitan Cempalagi—tak jauh dari area pasir putih yang kini mulai ditata sebagai kawasan wisata desa. Tetapi yang membuatnya istimewa bukan semata lanskap alamnya, melainkan kisah yang dikandung di dalamnya: sumpah perjuangan Arung Palakka, salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Sulawesi Selatan.
Gua Janci diyakini sebagai tempat Arung Palakka (Raja Bone ke-15 yang memimpin perlawanan terhadap hegemoni Kerajaan Gowa) mengucapkan ikrar suci yang lebih dikenal dengan sebutan Loko. Di lokasi tersebut terdapat bekas tapak kaki (hentakan kaki) yang disebut-sebut sebagai milik Aru Palakka. Selain bekas tapak kaki di bagian lain juga terdapat akar pohon yang membatu, masyarakat lokal menyebutnya Assingkerukeng (simpul). Kedua bagian ini inilah yang menjadikan kesakralan dari penyebutan sumpah atau ikrar seorang raja yang sedih melihat kesengsaraan rakyatnya. Konon, setelah kekalahan Bone dan Soppeng oleh Gowa, Aru Palakka merasa bahwa tak ada lagi tempat bagi dirinya di negeri Bugis (1660 M) dan memutuskan untuk mencari kekuatan untuk melawan Raja Gowa. Cerita ini hidup dalam ingatan masyarakat, diwariskan turun-temurun, namun tak banyak tercatat secara resmi dalam narasi sejarah nasional.
Sebagai narasi sejarah lokal, Gua Janci menyimpan potensi besar: bukan hanya sebagai ruang kenangan, tetapi juga ruang kontestasi memori. Siapa yang berhak menceritakan sejarah? Dalam versi resmi, Arung Palakka kerap digambarkan dengan nada ambivalen: pejuang kemerdekaan Bone sekaligus sekutu VOC. Di sinilah menariknya Gua Janci, ia bisa menjadi ruang alternatif untuk membaca sejarah dari perspektif masyarakat, bukan semata negara.
Namun hingga hari ini, Gua Janci tetap sunyi. Tak banyak wisatawan tahu keberadaannya. Tak ada pusat informasi, pemandu profesional, ataupun narasi visual yang menjelaskan makna sejarah tempat itu. Ia hanya muncul sesekali dalam program pengabdian masyarakat perguruan tinggi, atau unggahan media sosial mahasiswa KKN dan juga beberapa berita dari media cetak lokal. Potensi besar itu seolah terperangkap di balik lorong gelap gua yang belum disentuh narasi besar.
Padahal, di banyak tempat lain di dunia, situs-situs sejarah lokal telah menjadi tulang punggung pariwisata berbasis budaya. Gua tempat perjanjian suci, tempat pelarian, tempat pertapaan, semuanya bisa menjadi titik berangkat wisata edukatif yang tidak hanya menghibur, tapi juga menyadarkan. Sayangnya, di banyak daerah seperti Mallari, sejarah masih dipandang sebagai milik masa lalu yang tak perlu disingkap lagi, apalagi dimodernkan.
Kondisi ini bukan hanya soal keterbatasan infrastruktur, tapi juga persoalan kesadaran memori kolektif. Banyak masyarakat tak merasa perlu “menjual sejarah”, karena menganggapnya tidak relevan dengan kebutuhan hari ini. Sebaliknya, pemerintah daerah kerap hanya melihat potensi ekonomi, tanpa memperhatikan pentingnya kurasi narasi dan pelibatan warga dalam interpretasi sejarah itu sendiri.
Gua Janci adalah contoh konkret bahwa sejarah dan pariwisata seharusnya tidak dipisahkan. Ia bisa menjadi model pengembangan heritage tourism berbasis komunitas, jika ada kemauan untuk menjadikan warga sebagai pemilik cerita, bukan sekadar penjaga lokasi. Perempuan-perempuan di Mallari bisa dilibatkan sebagai pemandu narasi lokal. Anak-anak muda desa bisa memproduksi konten visual dan audio sejarah. Sekolah bisa menjadikan tempat ini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kebudayaan.
Tentu saja, semua ini memerlukan langkah awal yang sederhana, yakni menuliskannya kembali dalam ruang publik. Gua Janci perlu dibicarakan di luar desa. Perlu hadir dalam media, jurnal, dokumenter, bahkan film. Kisah Arung Palakka perlu didengar dari Mallari, bukan hanya dari halaman sejarah sekolah. Sebab jika tidak, situs itu akan terus menjadi ruang sunyi, dan sejarah hanya tinggal jejak tapak kaki yang makin pudar.
Sejarah tidak selalu hadir dalam monumen megah. Kadang ia bersembunyi di celah batu, di lorong gelap, di desa yang jauh dari pusat. Tapi justru di situlah sejarah paling otentik berbicara. Gua Janci sedang menunggu untuk dihidupkan kembali, bukan hanya sebagai objek wisata, tapi sebagai ruang dialog antara masa lalu dan masa kini, antara ingatan dan harapan.
Gua Janci bukan hanya milik Mallari. Ia adalah bagian dari ekosistem ingatan kolektif Bone, bahkan Sulawesi Selatan. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadikannya sebagai tempat “yang diceritakan”, tetapi juga sebagai ruang yang “dihidupkan kembali” dengan pendekatan yang berakar pada riset, partisipasi masyarakat, dan etika pelestarian.
Akhirnya, jika benar Arung Palakka pernah berikrar di tempat ini, maka kita pun hari ini perlu mengikrarkan sesuatu: bahwa kita bersedia menjadikan warisan sejarah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar simbol yang lapuk oleh waktu. Gua Janci adalah jendela masa lalu yang menanti untuk dibuka kembali, bukan untuk dikultuskan, tapi untuk dipahami dan dijaga bersama. (*/)