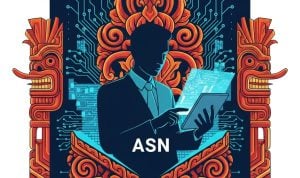Oleh: Yusran, S.Pd., M.Pd. (Guru Sosiologi SMA Islam Athirah Makassar)
“Manusia adalah sebuah pilihan, sebuah perjuangan, sebuah proses menjadi yang terus-menerus berlangsung. Manusia adalah melakukan migrasi (hijrah) tak terbatas, migrasi dalam diri sendiri, migrasi dari bumi menuju Tuhan: manusia adalah migran dengan jiwanya sendiri” (Shariati, 1979:93).
Kutipan dari Ali Shariati dalam On The Sociology of Islam menekankan bahwa manusia bukan sekadar makhluk biologis, tetapi entitas spiritual yang terus bergerak dan berproses. Hidup adalah perjalanan spiritual yang tak berkesudahan suatu perpindahan batiniah dari dunia menuju Tuhan. Dalam perjalanannya, manusia mengalami banyak bentuk perpindahan: dari kebodohan menuju pemahaman, dari egoisme menuju empati, dari dunia menuju akhirat. Perjalanan ini bermuara pada satu tujuan yakni penyatuan kembali jiwa dengan Sang Pemilik Jiwa.
Dalam konteks tersebut, Tuhan telah menitipkan intisari kehidupan kepada setiap makhluk bernyawa berupa jiwa. Dalam tradisi Sanskerta, jiwa disebut jiva, yang berarti “benih kehidupan”. Jiwa ini bukanlah entitas material, tetapi zat immaterial yang menjadi penggerak segala kesadaran manusia. Saat jiwa bersatu dengan tubuh, maka terbentuklah anima jiwa yang hidup, berpikir, merasa, dan bertindak.
Kebebasan berpikir adalah salah satu bentuk aktualisasi jiwa. Melalui pikiran, manusia mengekspresikan keberadaan spiritualnya secara subjektif dan objektif. Akan tetapi, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Jiwa selalu berada dalam tegangan antara inner freedom (kebebasan dari dalam diri) dan external determination (pengaruh luar), termasuk nilai-nilai agama dan norma sosial.
Dalam konteks inilah, agama memainkan peran penting sebagai pembimbing arah perjalanan jiwa manusia. Agama bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga sistem etika dan tanggung jawab sosial. Melalui agama, manusia diajarkan untuk hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang lain.
Pemahaman agama yang mendalam (verstehen) mendorong munculnya rasa simpati, solidaritas, dan pengorbanan. Ketika individu dengan sadar menjalankan nilai-nilai agama untuk menebar kebaikan dan menghapus egoisme, maka ia telah menghayati prinsip teodesi dalam hidupnya.
Teodesi, sebagaimana dijelaskan oleh Gottfried Leibniz dan diperluas oleh pemikir seperti Turner, adalah cara manusia memahami kebaikan Tuhan di tengah realitas penderitaan. Dalam perspektif ini, penderitaan bukanlah semata hukuman, tetapi juga ujian dan sarana penyucian jiwa. Kebaikan Tuhan menjadi nyata saat manusia mampu menampakkan kasih, membantu sesama, dan berbagi kebahagiaan, bahkan di tengah cobaan.
Konsep ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan realitas kematian. Dalam ajaran agama, kematian adalah pintu masuk menuju kehidupan abadi, proses pelepasan jiwa dari tubuh sebagai bentuk kembalinya manusia kepada Tuhan. Namun di tingkat sosial, kematian adalah momen krisis yang menyentuh kesadaran kolektif. Ia mengundang kehadiran, empati, dan solidaritas masyarakat.
Dalam budaya Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunal, kematian seseorang bukan hanya menjadi urusan keluarga inti, tetapi menjadi urusan bersama. Gotong royong menjadi manifestasi nyata dari moralitas kolektif. Ketika ada warga yang meninggal, tetangga, kerabat, dan teman sejawat secara spontan hadir membantu, baik secara tenaga, materi, maupun doa.
Mulai dari memandikan jenazah, menyiapkan makanan, menggali liang kubur, hingga mengatur proses pemakaman, semua dilakukan bersama-sama. Tidak ada imbalan, tidak ada kontrak, hanya ada kesadaran kolektif bahwa penderitaan satu anggota adalah penderitaan seluruh komunitas. Dalam momen duka ini, nilai-nilai teodesi menemukan wujudnya dalam praktik sosial: empati, pengorbanan, dan cinta kasih nyata.
Budaya gotong royong ini tidak hanya mencerminkan moralitas agama, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Ia adalah cerminan dari solidaritas mekanik (menurut Émile Durkheim) yang berakar pada kesamaan nilai dan keyakinan spiritual. Ketika satu jiwa pergi, seluruh komunitas mengiringinya dengan cinta dan doa. Kehadiran mereka di rumah duka adalah bentuk penghormatan, perenungan akan kefanaan, sekaligus penegasan bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri dalam menghadapi akhir hidupnya.
Refleksi kedukaan semacam ini menjadi instrumen pengingat kolektif bahwa setiap manusia akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, perbuatan baik dan hubungan sosial yang harmonis menjadi modal penting bagi jiwa agar kembali dalam keadaan bersih. Solidaritas yang muncul saat kematian bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga wujud iman, bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia ini, dan bahwa kebaikan yang ditanam hari ini akan menjadi cahaya bagi perjalanan jiwa menuju keabadian.
Manusia adalah pengembara spiritual. Ia berpindah dari fase ke fase, dari bentuk ke bentuk, dari kehidupan duniawi menuju keabadian. Dalam perjalanan itu, kebersamaan dan solidaritas menjadi bekal, sementara kematian menjadi titik temu antara dunia dan akhirat. Gotong royong dan empati bukan hanya budaya, tetapi jalan kembali menuju Tuhan.