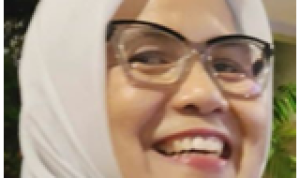Oleh: M. Aris Munandar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin/Anggota Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia
Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April sebagai momentum pembelajaran dan perjuangan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Perjuangan seorang R.A. Kartini mengasosiasikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki hak, seiras dengan laki-laki. Berangkat dari pembatasan yang menekan terhadap perempuan, Kartini menggelorakan semangat pembebasan agar perempuan Indonesia menjadi tiang penopang kemajuan dan eksistensi bangsa.
Menilik sedikit ke belakang, perjuangan RA Kartini dimulai pada tahun 1890-an hingga wafatnya pada tahun 1904.
Warisan monumental yang ditinggalkannya adalah gagasan emansipasi kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial (kompas.com). Kartini menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi perempuan sebagai pintu gerbang kebangkitan martabat dan peran perempuan di tengah masyarakat. Meski singkat, pengaruh perjuangannya besar, membangkitkan kesadaran kolektif perempuan akan hak-haknya.
Kartini sendiri adalah korban poligami. Ia menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, yang saat itu telah memiliki tiga istri dan tujuh anak. Situasi ini mencederai kebebasan pribadi Kartini dan menyoroti realitas sosial yang memperlakukan perempuan sebagai objek dalam sistem perkawinan yang bersifat memaksa. Dalam surat-suratnya, ia menyuarakan bahwa perempuan berhak menentukan jalan hidup, termasuk pasangan hidupnya (rri.co.id).
Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 408.347 kasus perceraian yang dilaporkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 314 kasus terjadi akibat kawin paksa (Sumber: https://databoks.katadata.co.id/). Data ini menunjukkan dampak negatif dari praktik perkawinan tanpa persetujuan, yang berujung pada ketidakbahagiaan dan perceraian.
Hukum kini bergerak lebih progresif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 10, mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, dapat dipidana hingga sembilan tahun dan/atau denda Rp. 200 juta. Pemaksaan tersebut mencakup perkawinan anak, perkawinan yang mengatasnamakan budaya, serta perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan (peraturan.bpk.go.id).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat dipidana, termasuk orang tua yang memaksa anaknya menikah. Hukum mengedepankan prinsip keadilan tanpa pandang bulu, sebagaimana maksim hukum: justitia non novit patrem nec matrem, solum veritatem spectat justitia yang berarti keadilan tidak mengenal ayah dan ibu, keadilan hanya memandang kebenaran.
Namun, ketentuan ini memiliki pengecualian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan ruang bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan apabila pihak laki-laki atau perempuan belum mencapai usia tersebut, dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti cukup.
Budaya sering kali menjadi pembenar dalam permohonan dispensasi. Padahal, Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan termaktub bahwa pemberian dispensasi harus mempertimbangkan moral, agama, adat, dan budaya. Namun, budaya tidak boleh dijadikan dalih untuk merugikan anak. Pencegahan perkawinan anak harus menjadi prioritas, walau ada tekanan budaya yang dilestarikan sebagian masyarakat.
Kartini menolak pemaksaan perkawinan dan memperjuangkan hak perempuan memilih jalan hidup. Semangat ini harus dilanjutkan dalam konteks hukum modern yang mengutamakan perlindungan anak dan perempuan, bukan melanggengkan tradisi yang berpotensi merugikan. Pemerintah harus aktif menyosialisasikan bahaya perkawinan anak dan pentingnya hak perempuan memilih pasangan hidup.
Budaya tidak bersalah, karena ia merupakan entitas sosial dari warisan nilai-nilai yang mencerminkan identitas dan norma masyarakat. Namun, interpretasi dan pelaksanaan budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti praktik perkawinan anak, perlu ditinjau ulang. Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, budaya dapat beradaptasi untuk melindungi hak anak dan perempuan tanpa kehilangan esensinya. (*/)