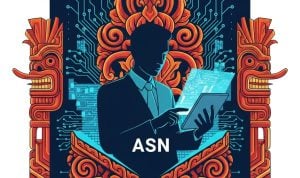Tulisan ini saya mulai dari komentar netizen dari kelompok Kajian Walanae Hermeneutik. Ini antara lain komentar mereka: “Sindikat uang palsu di perpustakaan UIN Alauddin adalah sebuah kealpaan kolektif”.
“Ketika kita mulai melupakan fungsi sebenarnya dari perpustakaan, kita membuka peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan. Perpustakaan, yang seharusnya menjadi benteng bagi pendidikan dan intelektualitas, justru menjadi tempat yang memungkinkan aktivitas ilegal berkembang tanpa gangguan. Ini adalah hasil dari kelalaian kita sebagai komunitas akademik. Kita telah menganggap remeh ruang ini. Pada akhirnya, ruang itu pun membalas ketidakpedulian kita dengan cara yang tidak terduga.”
Yang lain berkomentar: “Perpustakaan saja sudah bisa cetak uang palsu. Apakah mungkin nanti akan mencetak Intelektual palsu juga?”
“Kayaknya uang palsu itu cuma memberikan hikmah kepada kita bahwa dari pada intelektual palsu terus dicetak yang tujuannya untuk menghasilkan uang. Kenapa bukan langsung cetak uang palsunya supaya tidak ada lagi kejar Intelektual palsu (gelar tanpa ilmu)”
“Sederhana saja dalam pikiranku, oknumnya yang tidak puas dengan dunianya, padahal masih banyak saudara kita yang masa depannya suram, namun tidak berkaca dari situ. Kurang apalagi tunjangan dan gaji seorang kepala perpustakaan. Betullah kata pepatah Bugis: “cecceng ponna, sapu ripale cappana” (kerakusan pada ujungnya akan menghasilkan kehampaan). Niat menumpuk harta, namun ujungnya habis, tidak bersisa sama sekali, … sudah ditangkap dipecat pula… tidak lama hartanya juga disita. Aku bingung pikirkan, entah apa yang ada di benaknya, sampai mau nekad begitu…” “Kalau orang miskin nekad, itu biasa, untuk mengubah nasib yang susah. Tetapi, intelektual dengan hidup yang serba berkecukupan, apalagi yang mau dia ubah? (“atikku ilautang, agapi musappa, muruntu manenni ‘warangpareng’, ‘jabatan’, ‘strata sosial’?”