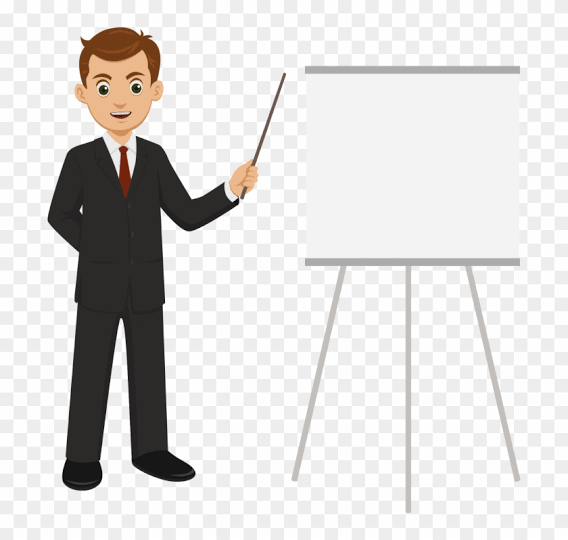Hasil survei tentang gaji dosen Indonesia mengguncang jagat maya. Banyak pihak, selain dari kalangan dosen sendiri tentunya, yang baru tahu persisnya bagaimana kondisi dan nominal gaji dosen sebenanrya.
Bukan apa – apa, selain dosen nya sendiri kadang tak menunjukkan penampilan yang mencerminkan kondisi upahnya, kebanyakan pihak memang menganggap bahwa ketika seseorang itu diterima menjadi dosen, maka serta – merta dianggap “sukses”. Padahal, di balik punggung seorang dosen, yang variasi status dan model pengupahannya juga beragam, tersimpan beban kerja yang “berat”, dengan upah yang nyaris “sekarat”, alias tak layak dan tidak sepadan.
Wacana yang beredar juga dalam merespons kondisi model pengupahan dan aturan baru mengenai jenjang karir dosen berikut tunjangan yang menyertainya adalah pembentukan serikat dosen. Hal ini tentunya adalah sebuah langkah maju dengan anggapan bahwa dalam relasi kerja sekarang ini, dosen tak ubahnya sebagai buruh pekerja kasar. Seringkali memang diperlakukan kasar meski dengan penampakan yang dihalus – haluskan.
Dosen sebagai buruh tentu banyak benarnya. Namun, menyederhanakan seorang dosen sebagai buruh semata seperti mengesampingkan “kompetensi” dan “tugas profetik” seorang dosen sebagai intelektual yang memungkinkannya tak sesederhana menganggapnya atau mendakukan diri sebagai “buruh” sebagaimana dipahami banyak kalangan.
Mengemukakan dosen sebagai sebuah “profesi” tentu bukan puka untuk memisahkan diri dengan status buruh apalagi memisahkan diri dari perjuangan buruh. Tidak sesederhana itu juga. Akan tetapi, selain relasi kerjanya dengan “tuan kampus” tempatnya bekerja, yang menjadikan posisi dosen memang tak ubahnya sebagai buruh upahan, dosen juga mesti dipandang, dan juga sepatutnya memandang diri sebagai profesi yang memiliki kompetensi dan tugas profetik di masyarakat. Dari dua poin ini saja memang, sungguh amat keterlaluan jika negara dan swasta masih saja mengupah dosen secara rendah. Sungguh terlalu.
Dosen sebagai profesi juga nantinya akan berimplikasi pada tunjangan profesi yang menyertainya dan pembayaran gaji per jam yang pantas bagi setiap dosen yang mengajar di kelas dan membimbing mahasiswa, melakukan penelitian dan pengabdian di luar kelas. Hal ini juga tentu tak sesederhana dengan tunjangan “sertifikasi dosen” yang makin dibuat rumit dan makin diribet-ribetkan belakangan ini, yang kesannya hanya supaya tidak banyak dosen yang mendapatkannya dan negara tidak keluar duit banyak.
Teranglah, bahwa efisiensi sebagai jangkitan neoliberalisme beroperasi di sini. “Pelitisme” anggaran menjadi dasar kebijakan hingga rumitnya aturan dan pelaksanaannya yang seperti dibuat – buat sedemikian rupa. Memalukan sekali, karena ujung-ujungnya ketahuan juga. Negara memang “pelit” kepada dosennya. Tapi, taga saja membebankan kerja yang beratnya tak ketulungan.
Apa pemerintah melihat dosen tak ubahnya seperti romusha di jaman penjajahan?
Upah tak pantas
Hasil riset kolaborasi sejumlah akademisi yang dirilis
pada artikel di conversation.com bertajuk Berapa gaji dosen? Berikut hasil survei nasional pertama yang memetakan kesejahteraan akademisi di Indonesia, pada 4 Mei 2023 baru – baru ini mencuat di percakapan sehari – hari bak cendawan di musim hujan. Kenyataan ini seperti menampar muka pemerintah, terutama kementerian pendidikan, kementerian keuangan, dan kementrian aparatur sipil negara, beserta instansi terkait. Mereka, para pejabat di kementrian ini, juga atasan tertingginya, seperti merayap tak berani bersuara merespons “kegaduhan” yang terjadi. Lakunya mirip pengecut saja. “Ibarat lempar tangan sembunyi batu”.
Tulisan perihal di atas juga di platform yang sama pernah dirilis pada 10 November 2022 dengan judul Pakar Menjawab: Seperti apa potret gaji dan realitas kesejahteraan dosen di Indonesia? Mestinya, dari tulisan ini saja, jika ada itikad baik pemerintah, aturan baru yang lebih menekankan peningkatan signifikan gaji dosen dan standar penggajian yang pantas, sudah dikeluarkan. Tapi, nyatanya tidak, dan memilih diam saja seolah tidak peduli. Penjelasan memuaskan pun tak kunjung datang. Payah memang.
Jika pemerintah negeri ini punya malu, tamparan hasil riset di atas mestinya membuatnya lekas bertindak. Bukan hanya malu di hadapan pemerintah dan warga serta dosen di tetangga sebelah, tapi juga malu di hadapan warga sendiri. Ternyata, begitu cara pemimpin mereka memperlakukan kaum cerdik pandainya yang diharapkan oleh rakyat mencerdaskan anak – anak mereka. Kejengkelan itu tentu menjadi – jadi ketika menengok bagaimana rezim sekarang ini jor – joran menggelontorkan uang untuk proyek fisik, dan tak ketulungan memberikan kesejahteraan di kementerian tertentu, tapi upah dan tunjangan dosen, juga gurunya, begitu memilukan.
Patut dipertanyakan rupanya sisi kemanusiaan rezim pemerintahan hari ini. Jangan – jangan sudah berada di titik minus. Celaka sekali jika sudah demikian.
Simplifikasi Pemburuhan
Kembali ke soal dosen sebagai buruh dan dosen sebagai profesi. Keduanya bagi saya sebagai penulis adalah dua hal yang tak perlu dipertentangkan. Apakah dosen itu adalah buruh atau profesi? Jawabannya adalah keduanya. Dosen adalah buruh di hadapan tuan kampus, dan profesi dengan tanggung jawab “profetik” di hadapan masyarakat yang dilayaninya dengan keunggulan “kompetensi”-nya.
Dengan pandangan itu, institusi pendidikan yang dijangkiti virus dan bakteri neoliberal, mesti dihadapi dengan keberadaan serikat dosen. Itu sudah tepat. Namun, tugas – tugas profetik yang mulia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam tridharma, tetap harus dijunjung tinggi dan dijadikan alas dasar dalam menetapkan tunjangan yang pantas, dalam hal ini bayaran tinggi di atas rata – rata pekerjaan lain. Ini juga perlu diperjuangkan. Menghadapi musuh yang ngelesnya makin canggih memang tak cukup dengan satu jurus dan ilmu kanuragan terbatas.
Seperti jurnalis, dia adalah buruh di hadapan perusahaan media tempatnya bekerja. Namun, jurnalis adalah sebuah profesi dengan tanggung jawab “profetik” dengan kompetensi menuliskan “jurnal” atau “berita” untuk dikonsumsi oleh publik. Sehingga, jurnalis adalah pelayan masyarakat dalam menyajikan informasi dalam bentuk berita kepada masyarakat. Begitupula dokter yang bekerja di instansi pemerintah atau klinik swasta, relasi kerjanya mendua diantara buruh negara dan swasta dengan profesi dokter yang diikat dengan kompetensi dan kode etik.
Olehnya, bukan hanya upah sebagai buruh yang pantas didapatkan, namun tunjangan profesi sebagai dokter, jurnalis, dan dosen. Pengacara juga begitu. Apoteker pun demikian. Insinyur apatahlagi. Singkatnya, tak pantas mendapat “gaji rendah”, terlebih dilihat dan melihat diri sebagai buruh semata dengan mengesampingkan peran profetik.
Serikat dosen dan tanggung jawab profetik
Profesi – profesi dengan “tugas profetik” di atas sebagai implikasi dari “kompetensi” yang dimilikinya dalam pelayanan masyarakat, tak pantas memang jika “diburuhkan” semata oleh negara dan perusahaan. Begitupula bagi dosen dalam memandang dan mendefinisikan dirinya, tak sesederhana juga memandang diri semata sebagai buruh dan mengesampingkan kapasitas “kompetensi khusus” yang menjadi karakteristik utama lahirnya sebuah “profesi”.
Kalaulah “pemburuhan” itu sebagai upaya menyadarkan sesama untuk membentuk serikat sebagai wadah perjuangan bersama, tentu sangat baik. Hanya saja, patutnya tidak berhenti di situ. Tuntutan untuk tunjangan yang lebih “pantas” sebagai “profesi” — bukan seperti model sertifikasi dosen sekarang yang seperti sengaja dibuat-buat susah — patut digaungkan juga bersamaan dengan perjuangan menuntut upah yang layak sebagai “buruh”.
Karena, tugas dosen adalah selain “mengabdi kepada majikan” pemberi upahnya, juga lebih besar lagi memiliki tugas mulia dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Panjang umur perjuangan dosen – dosen Indonesia. (*)
OLEH : Nasrullah, Dosen Unmul dan alumni Unhas